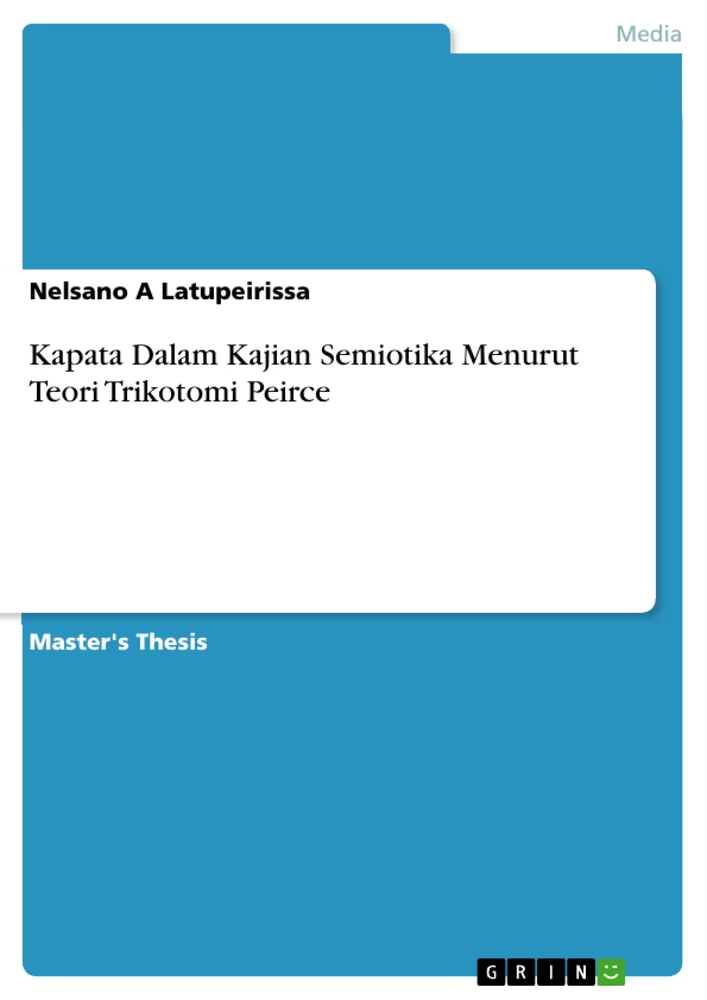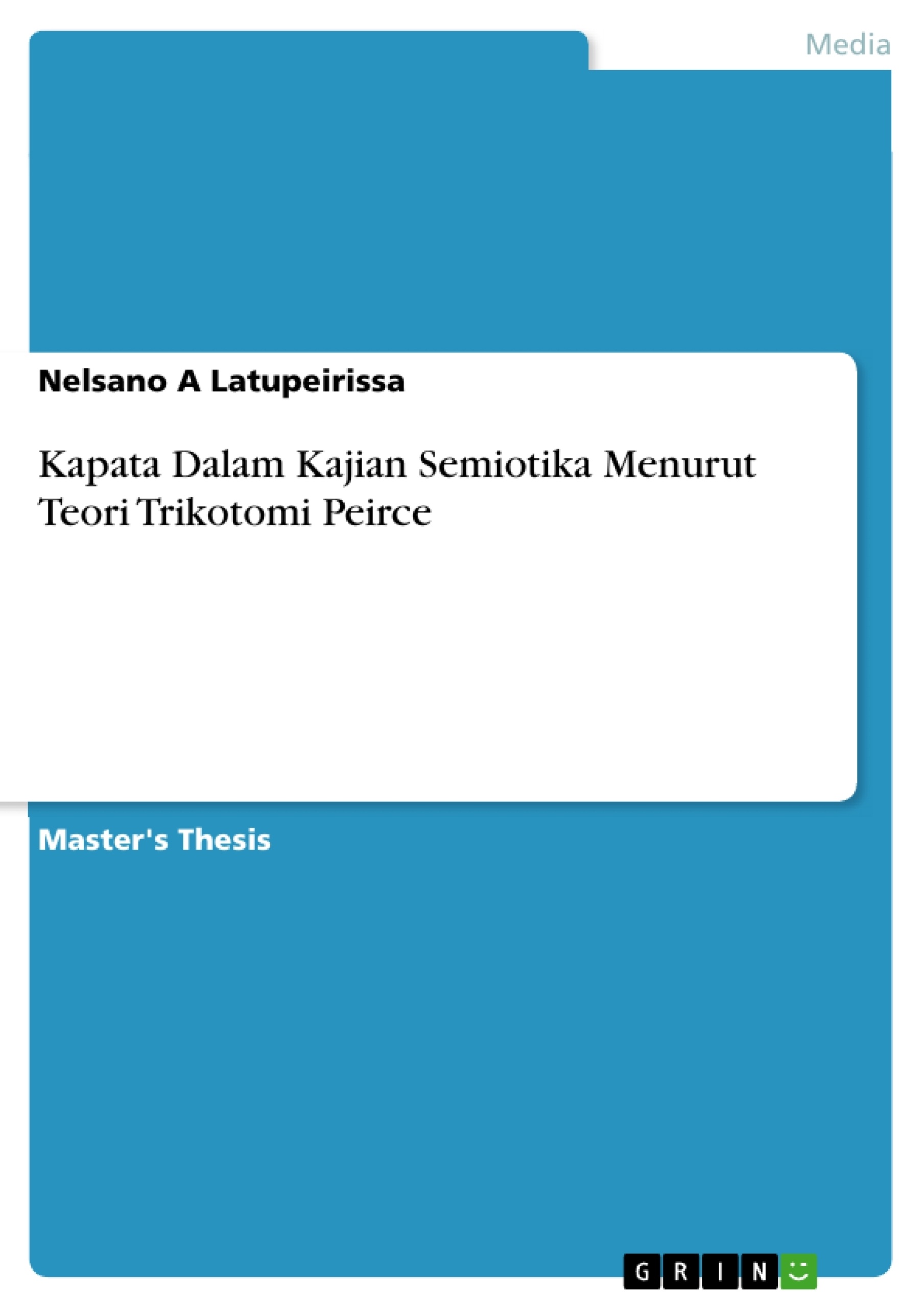There is a genre of folksong in Central Maluku known as Kapata. It is such a powerful and sacred chant, that in general is sung or being recited as a poem. Kapata is usually performed at traditional ritual ceremony in Maluku, such as,during the local king (Raja) coronation, in renovating the traditional house (baeleo),and for the installation of a new building. However, this research is focused onthe Kapata, which was per-formed during the coronation of Negri Allang’s King in Central Maluku. This research is using etnomusicological approach, in order to examine what kind of signs that may have attributed to Kapata, by using semiotics analysis based on Peirce’s trichotomy theory. In addition, another theory of Merriam’s three level of musical activities, namely the concept, behavior and musical sound itself, is used in investigating how Kapata was being transmitted.
Inhaltsverzeichnis
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERNYATAAN
ABSTRACT
ABSTRAK
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR NOTASI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Arti Penting Topik
C. Rumusan Masalah
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
2. Manfaat Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
B. Landasan Teori
C. Sekilas tentang Kebudayaan Negeri Allang
1. Asal usul Penduduk dan Terbentuknya Negeri Allang
2. Kehidupan Budaya Masyarakat Negeri Allang
a) . Sistem Kepercayaan
b) . Sistim Kekerabatan
c) . Upacara Ritual di Negeri Allang
1) . Upacara Perkawinan
2) . Upacara Panas Pela
3) . Upacara Pelantikan Raja
BAB III METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
B. Pemilihan Sampel
C. Tahap Pengumpulan Data
D. Metode Analisis Data
E. Hasil Pengumpulan Data
1. Musik di Maluku
a) . Pengaruh musik Timur Tengah
b) . Pengaruh Musik Eropa
c) . Musik Asli Maluku
1) . Pengertian Kapata
2) . Fungsi Kapata
3) . Jenis-jenis Kapata
a) . Kapata Hasurite
b) . Kapata Mako-mako
c) . Kapata Cakalele
BAB IV PEMBAHASAN
A. Makna Tanda Kapata yang disajikan dalam Pelantikan Raja
1. Kapata dalam Pelantikan Raja Allang
a. Vokal dan Lirik
b. Instrumen Musik
2. Deskripsi dan Analisis Struktur dan bentuk Kapata
a. Lagu dari Rumah Tua Huwae Ke Baeleo
b. Lagu dari Baeleo ke Rumah Patty
c. Lagu dari Rumah Patty ke Rumah Parintah
3. Tanda-tanda dan Makna Kapata
a. Tanda-tanda dalam Kapata
b. Makna Kapata
1) . Nada
2) . Melodi
3) . Ritme
4) . Figure
5) . Semi Frase
6) . Frase
7) . Periode
B. Transmisi Kapata
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
SUMBER ACUAN
A. Literatur
B. Narasumber
C. Diskografi
RIWAYAT HIDUP PENULIS
Gambar 1. Relasi Segitiga Tanda
Gambar 2. Model dari teori yang dikemukakan Alan P. Merriam
Gambar 3. Peta Pulau Ambon dan letak negeri Allang, yang ditandai dengan lingkaran merah
Gambar 4. Musik sawat, salah satu pengaruh musik Timur Tengah di Maluku
Gambar 5. Musik hadrat, juga merupakan salah satu pengaruh musik Timur Tengah di Maluku
Gambar 6. Suling bambu, salah satu pengaruh musik Eropa di Maluku, yang menggunakan tangganada diatonik
Gambar 7. Suling bass dalam ansambel suling bambu di Maluku, biasa digunakan dalam ibadah di gereja
Gambar 8. Musik totobuang, salah satu musik tradisi Maluku
Gambar 9. Musik tahuri, salah satu musik tradisi di Maluku
Gambar 10. Tifa Maluku
Gambar 11. Proses semiosis penggunaan tujuh buah nada merujuk pada tujuh buah kampung
Gambar 12. Proses semiosis penggunaan delapan buah nada merujuk pada delapan soa
Gambar 13. Proses semiosis penggunaan sembilan buah nada merujuk pada kelompok PataSiwa
Gambar 14. Kontur melodi lagu yang dinyanyikan dari rumah tua Huwae ke baeleo
Gambar 15. Kontur melodi lagu yang dinyanyikan dari baeleo ke rumah tua Patty
Gambar 16. Kontur melodi lagu yang dinyanyikan dari rumah tua Patty ke rumah parintah
Gambar 17. Proses semiosis ikon metafora
Gambar 18. Proses Transmisi kapata
DAFTAR NOTASI
Notasi 1. Motif-motif permainan tifa Maluku
Notasi 2. Lagu dari rumah tua Huwae ke baeleo
Notasi 3. Frase, anak frase, dan figure dalam lagu yang dinyanyikan dari rumah tua Huwae ke baeleo
Notasi 4. Lagu dari baeleo ke rumah tua Patty
Notasi 5. Bagian, frase, Lagu Anak frase dan figure dalam lagu yang dinyanyikan dari baeleo ke rumah tua Patty
Notasi 6. Lagu dari rumah tua Patty ke rumah parintah
Notasi 7. Frase, anak frase, dan figure dalam lagu yang dinyanyikan dari rumah tua Patty ke rumah parintah
Notasi 8. Contoh figure
Contoh 9. Contoh anak frase
Notasi 10. Contoh frase
Notasi 11. Contoh sebuah periode
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan.
Saya bertanggung jawab atas keaslian karya saya ini, dan saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini.
Yang membuat pernyataan
Nelsano Anesry Latupeirissa
KAPATA DALAM KAJIAN SEMIOTIKA MENURUT TEORI TRIKOTOMI PEIRCE
Writen Report Project
Graduate Program of Indonesian Art Institut Yogyakarta, 2011
By Nelsano Anesry Latupeirissa
ABSTRACT
There is a genre of folksong in Central Maluku known as Kapata. It is such a powerful and sacred chant, that in general is sung or being recited as a poem. Kapata is usually performed at traditional ritual ceremony in Maluku, such as, during the local king (Raja) coronation, in renovating the traditional house (baeleo), and for the installation of a new building. However, this research is focused on the Kapata, which was performed during the coronation of Negri Allang’s King in Central Maluku.
This research is using etnomusicological approach, in order to examine what kind of signs that may have attributed to Kapata, by using semiotics analysis based on Peirce’s trichotomy theory. In addition, an-other theory of Merriam’s three level of musical activities, namely the concept, behavior and musical sound itself, is used in investigating how Kapata was being transmitted.
The analysis has shown that Kapata which was performed at the aforesaid Negri Allang had some incredible mind effect to its community; where it contains the essential cultural codes, that in certain level may have been considered as the Maluku’s higher cultural symbol. Amongst which, those symbols appeared in the seven-tones as indexical sign that referring to this community’s seven earliest Negri, that were enacted by their ancestors; in Negri eight-tones as indexical sign referring to eight soa in the social life of Allang community; in nine-tones as indexical sign referring to the system of social life, namely Patasiwa group. Kapata was transmitted orally, though a kind of written notation is also found in Kapata ’s teaching practices recently, that it has some new impact to the singing style of Kapata.
Kapata has given a lot of contributions to the musical development in Maluku region. The ancestors of Maluku people in the earliest time have inherited such intangible heritages in showing that they possessed a highly sense of humanity and musical aesthetics through the musical symbols depicting the reality of social life, either the past, or the present and the future.
Keywords: Kapata, semiotic, trichotomy, signs, transmission
KAPATA DALAM KAJIAN SEMIOTIKA MENURUT TEORI TRIKOTOMI PEIRCE
Pertanggungjawaban tertulis
Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2011
Oleh Nelsano Anesry Latupeirissa
ABSTRAK
Di daerah Maluku Tengah nyanyian rakyat/ folk song lazimnya disebut kapata. Kapata adalah ucapan-ucapan yang suci dan yang mempunyai kekuatan, biasanya dinyanyikan atau dilafalkan seperti sebuah sajak. Kapata biasanya disajikan dalam upacara ritual adat di Maluku seperti pelantikan raja, pembongkaran dan pembangunan rumah adat (baeleo), dan peresmian rumah adat. Penelitian ini memfokuskan pada kapata yang disajikan dalam pelantikan raja di negeri Allang Maluku Tengah.
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan etnomusikologi. Untuk mengetahui tanda-tanda apa saja yang ada pada kapata, akan dilakukan analisis semiotika dengan menggunakan teori dari Peirce tentang trikotomi. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana proses transmisi kapata, digunakan teori dari Merriam tentang tiga tahapan dalam analisis musik yaitu, konsep, bunyi musik dan perilaku.
Hasil analisis menunjukan bahwa kapata yang disajikan dalam acara pelantikan raja memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap masyarakat Allang, bahwa negeri/kampung tersebut memiliki kode-kode kultural yang sekaligus merupakan simbol-simbol kebudayaan Maluku. Simbol-simbol yang nampak diantaranya adalah penggunaan tujuh buah nada sebagai tanda indeksikal yang merujuk pada objek perkampungan masyarakat Allang di daerah pegunungan yang ditemukan oleh para leluhur imigran dari Seram, yang dianggap sebagai negeri mereka yang lama sebelum menetap di negeri yang sekarang ini; delapan buah nada sebagai tanda indeksikal yang merujuk pada objek sistem kehidupan sosial orang Allang yang tergabung dalam delapan soa; sembilan buah nada sebagai tanda indeksikal yang merujuk pada objek sistem kehidupan sosial orang Allang yang tergabung dalam kelompok patasiwa. Kapata ditransmisikan secara oral, meski saat ini sudah mulai menggunakan notasi dalam pembelajarannya. Ini antara lain berdampak pada sedikit berubahnya gaya nyanyian kapata, yang menjadi lebih ‘rapi.’
Lagu ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkem-bangan musik di daerah Maluku. Para leluhur orang Maluku telah memiliki kejeniusan sensitifitas humanis dan estetis musik lewat simbol-simbol musikal yang mengukapkan kenyataan sosial masyarakat baik masa lalu, kini dan masa yang akan datang.
Kata kunci: Kapata, semiotika, trikotomi , tanda-tanda, transmisi
*****
“ Ora et labora, biar lambat tapi pasti”
“Jang ale tanya apa yang negri akang kasi par ale, tapi tanya par ale pung diri, apa yang ale su kasi par ale pung negri. Sapa angka negri, negri angka dia.”
*********
KATA PENGANTAR
Daerah Maluku memiliki kekayaan budaya yang bernilai luhur. Keluhuran kebudayaannya terletak pada suatu untaian falsafah atau pandangan hidup yang mewarnai seluruh kreasi kebudayaan masyarakat. Salah satu kekayaan budaya daerah Maluku adalah budaya musik yang sampai sekarang ini menjadi kebanggaan masyarakat dan pemerintah. Perkembangan budaya musik di Maluku, khususnya secara akademis, dirasa sangat jauh tertinggal dengan daerah yang lain di Indonesia. Keadaan yang demikian menggugah penulis untuk terjun langsung dalam mengisi kelangkaan tersebut dengan mengikuti studi lanjut pada tingkat strata dua, walaupun dengan biaya mandiri tanpa bantuan dana dari pemerintah Provinsi Maluku maupun lembaga-lembaga donatur lainnya. Saat ini penulis telah berada pada tahap akhir dari kegiatan studi ini, yaitu telah melakukan penulisan tesis sebagai tugas akhir.
Puji syukur yang tulus penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang memungkinkan semua ini terjadi hal yang paling berarti dalam seluruh perjuangan studi ialah keberhasilan, bukan semata-mata karena hebat dan kuatnya penulis tetapi semua itu karena cinta Tuhan Yesus Kristus selalu bersama penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister pengkajian seni pada program pasca sarjana Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.
Dalam penulisan tesis ini, penulis mendapat bantuan dan dorongan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih kepada Prof. Dr. Victor Ganap, M.Ed., selaku pembimbing tesis, yang telah meluangkan waktunya untuk mengkoreksi dan memberikan komentar-komentar terhadap tulisan ini. Tidak lupa ucapan terima kasih juga disampaiakn kepada Prof. Dr. Djohan, M.Si., Prof. Dr. Triyono Bramantyo P.S., M.Mus.Ed., Ph.D., Prof. DR. Dwi Marianto, MFA, PhD., Prof. Dr. I Wayan Dana, S.S.T., M.Hum., Dr. G.R. Lono Lastoro Simatupang, M.A., serta semua pengajar dan staf di Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Terima kasih juga kepada para informan di negeri Allang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi-informasi untuk melengkapi data tesis ini. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Maluku yang telah memberikan ijin untuk saya melakukan penelitian ini., Kepala Taman Budaya Provinsi Maluku dan para stafnya, dimana telah memberikan kesempatan untuk saya mendapatkan pustaka-pustaka tentang objek penelitian ini; Bapak Raja Negeri Allang dan staf Negeri Allang serta masyarakatnya yang telah memberikan segala sesuatu yang selama penulis melakukan penelitian; Bapak P. Huwae dan istri serta anak- anak dan keluarga yang telah menampung saya selama melakukan penelitian. Terima kasih kepada guru-guru saya di SD, SMP, dan SMU, yang telah memberikan begitu banyak ilmu yang ternyata sangat berguna saat ini. Terima kasih kepada Pdt. Christian Tamaela, M.Th., Agustinus Gaspersz, M.Sn yang telah memberikan rekomendasi bagi penulis untuk melanjutkan studi ini; Rentje Alfons, S.Sn., Bartje Istia., dan teman-teman musisi di Kota Ambon yang telah memberikan bantuan lewat pengetahuan musik Kapata kepada penulis selama melakukan penelitian. Terima kasih juga kepada Nathalian H.P.D.P., Ayub Prasetyo, S.Sn., La Ode Karlan, S.Pd, Yulianto, S.Sn., Helena Limbong, S.Sn., Eva Pitaloka, S.Sn., dan Oriana Tio Nainggolan, S.Sn., yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi selama masa-masa perkuliahan hingga sampai pada saat ini; Dani Amaputra Pattinaja, S.Si., Ronaldo B Alfons, S.Sn., Thony Alfons., Yohanes Lengkong, S.Si., Marcelo Lerebulan dan seluruh alumni SMA Negeri 2 Ambon sebagai mantan murid-muridku yang sementara ini berada di Jogjakarta yang telah memberikan banyak bantuan selama saya menempuh studi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Papi Tjak Latupeirissa dan Ibunda mama Bata Latupeirissa, atas semua dukungan baik moral dan materi serta pengertian yang diberikan; kepada kakak, adik, serta keponakan-keponakan yang juga selalu membantu dan menyediakan berbagai fasilitas yang sangat meringankan penyelesaian tesis ini; dan khususnya saya ucapkan terima kasih kepada kedua anak terkasih Kakak Lerry dan Adik Grandi, atas dorongan semangat serta segala bantuannya. Semua karya ini ku persembahkan pada kalian.
Semoga tesis ini dapat menjadi sumbangan bagi dunia kajian musik secara khusus, dan seni secara umum, terutama di tanah Maluku. Penulisan tesis ini dapat digunakan sebagai salah satu pedoman dalam pengembangan musik di daerah tercinta Maluku, dan demi tercapainya suatu pembinaan musik yang lebih baik. Penulis menyadari sungguh bahwa penulisan ini penuh dengan keterbatasan dan kekurangan baik itu dari segi penulisan, tata bahasa, maupun uraian materi. Oleh sebab itu saran dan kritik dari semua pihak, khususnya, musisi-musisi yang ada di daerah Maluku sangat diharapkan guna penyempurnaan tulisan ini.
Yogyakarta, Juni 2011
Nelsano Anesry Latupeirissa
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tanah Maluku atau daerah “Seribu Pulau” sejak dahulu terkenal dengan dua kelompok sosial masyarakat, yaitu Kelompok Lima dan Kelompok Sembilan. Kedua kelompok sosial ini dijumpai baik di Maluku Utara, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, dengan istilah yang berbeda, yaitu di Maluku Utara dikenal dengan nama Uli-Siwa dan Uli-Lima, di Maluku Tengah dikenal dengan nama Pata-Siwa dan Pata-Lima, dan Maluku Tenggara dikenal dengan sebutan Ur-Siwa dan Ur-Lima (Pattykaihatu et al. 1977: 24).
Daerah Maluku memiliki kekayaan budaya yang bernilai luhur. Keluhuran kebudayaannya terletak pada suatu untaian falsafah atau pandangan hidup yang mewarnai seluruh kreasi kebudayaan masyarakat. Hal itu tampak dari berbagai ragam upacara adat, pola perilaku, ragam kesenian rakyat yang selalu melukiskan kuatnya filosofi masyarakat, sebagai suatu perlukisan dari pandangan hidup yang dianut masyarakat.
Kesenian rakyat merupakan suatu produk kebudayaan masya-rakat, sehingga dapat disebut juga dengan istilah seni etnik (ethnic art), dan biasanya dilestarikan melalui tradisi lisan (oral tradition). Kesenian rakyat umumnya terdiri dari lagu, tari, permainan rakyat, cerita rakyat (cerita anak-anak sampai orang dewasa dari para leluhur), dan pada dasarnya merupakan ekspresi seni yang hidup, berkembang dan terkenal atau populer dalam etnik lokal tertentu. Jenis-jenis seni ini biasanya dinamakan folklore. Folklore terdiri dari kata folk berarti rakyat dan lore yang berarti unsur-unsur tradisi dalam suatu budaya tertentu (Mack, 1995: 13).
Kapata merupakan salah satu bentuk kesenian rakyat yang terdapat di Maluku, yakni termasuk kategori nyanyian rakyat (folksong), dan dalam konteks yang lebih luas, termasuk sebagai kesenian rakyat. Menurut Jan Harlod Bruvand, nyanyian rakyat (folksong) adalah suatu genre atau bentuk folklore yang terdiri dari syair dan melodi, yang beredar secara lisan di antara anggota kolektif tertentu, berbentuk tradisional, serta banyak mempunyai varian (Danandjaja, 1986: 141). Nyanyian rakyat diwariskan melalui tradisi lisan (oral tradition) dari orang-orang tertentu, sebagai warisan budaya yang diteruskan untuk mengetahui pesan-pesan para leluhur (Lomax, 1986: 274).
Kapata merupakan salah satu seni musik tradisi Maluku sekaligus bagian dari sejarah tradisi bertutur di Maluku yang masih eksis sampai saat ini, dan biasanya kapata dinyanyikan atau dilafalkan seperti sebuah sajak. Kapata sebagai sebuah nyanyian, biasanya dinyanyikan dalam upacara ritual adat di Maluku seperti pelantikan raja, pembongkaran dan pembangunan rumah adat (baeleo), peresmian rumah adat. Apabila dinyanyikan dalam upacara ritual, nyanyian ini diyakini memiliki kekuatan-kekuatan magis yang serta-merta mempengaruhi sensitivitas kebudayaan dan spiritual masyarakat. Ada suatu kekuatan transendental yang dirasakan berpengaruh terhadap seseorang ketika menyanyikan dan mendengarkan lantunan kapata. Dalam kondisi itu orang tersebut terhisab ke dalam arakan upacara, dan seperti terbawa ke dalam alam ekstasi, sehingga daya imaginasinya pun hanyut ke dalam imaginasi budaya masyarakat setempat. Kapata pada umunya hanya dikuasai oleh masya- rakat Maluku golongan tua saja, yakni mereka yang telah berusia lanjut dan mereka ini menduduki peran-peran penting sebagai pemangku adat atau tua-tua adat dalam masyarakat (hasil wawancara bersama nara sumber Mei 2011).
Kapata, dalam pandangan masyarakat Maluku merupakan nyanyian yang mengandung nilai kesakralan yang diwariskan oleh para leluhur. Selain itu, kapata sebagian besar, atau hampir seluruhnya merupakan nyanyian-nyanyian tua yang muncul jauh pada masa lalu dan tidak diketahui siapa penciptanya. Nyanyian-nyanyian ini mengandung kekua- tan pesan asli (original message) yang mampu menjelaskan mengenai sisi- sisi sejarah, tempat-tempat dalam mitologi orang Maluku, dan berbagai falsafah kehidupan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kapata, sebagai suatu jenis lagu atau musik, terkait dengan itu ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa musik dapat diasosiasikan atau dianggap serupa dengan bahasa (lihat, misalnya, Agawu, 2009; Feld, 1974).
Seni, tak terkecuali musik, merupakan kreasi bentuk simbolis dari perasaan manusia. Bentuk-bentuk simbol seni tidak hanya menyampaikan “makna” atau meaning untuk dimengerti, tetapi lebih sebagai suatu “pesan” atau import untuk diresapkan. Hanya ada dua hal yang dapat dilakukan terhadap makna, yakni dapat dimengerti atau tidak dimengerti. Akan tetapi, terhadap pesan, terutama dalam seni, setiap orang dapat tersentuh secara mendalam. Di sinilah terdapat hubungan antara makna dan pesan pembentukan simbol terutama dalam produk kebudayaan dari suatu masyarakat (Hadi, 1999: 317).
Makna merupakan sesuatu yang erat kaitannya dengan pandangan- pandangan dari mereka yang menggunakan sesuatu itu. Demikian pula halnya dengan kapata. Bagi masyarakat di luar kebudayaan Maluku, kemungkinan besar kapata tidak memiliki arti apapun. Akan tetapi, bagi masyarakat Maluku, lagu ini memiliki arti tertentu yang antara lain merepresentasikan perjalanan sejarah, kebudayaan serta falsafah hidup mereka.
B. Arti Penting Topik
Kapata sebagai bagian dari produk kebudayaan masyarakat di Maluku merupakan sebuah kebanggaan yang perlu dilestarikan sebagai ekspresi dari nilai-nilai budaya lokal sehingga tidak terdesak oleh pengaruh arus budaya global. Permasalahan di atas memang sangat memprihatinkan dan menuntut kita untuk mencari bentuk yang komu- nikatif, sehingga beruntung saat ini kapata masih dikuasai oleh mereka yang berusia lanjut. Sebaliknya dikhawatirkan bagaimana seandainya mereka sudah tidak ada lagi, sehingga, kapata juga akan turut tenggelam bersama dengan kepergian mereka. Oleh sebab itu kapata ini perlu diteliti dan didokumentasikan dalam bentuk tulisan ataupun audio-visual guna perkembangan kapata sebagai salah satu bentuk seni tradisi Maluku di kemudian hari.
C. Rumusan Masalah
Dalam pandangan masyarakat Maluku, umumnya kapata merupa- kan nyanyian yang mengandung nilai-nilai filosofi dan kesakralan yang diwariskan oleh para leluhur dan biasanya digunakan dalam setiap kegiatan ritual adat. Selain itu, kapata sebagian besar, atau hampir selu- ruhnya merupakan nyanyian-nyanyian tua yang muncul jauh pada masa lalu dan tidak diketahui siapa penciptanya. Keadaan yang demikian menimbulkan pertanyaan:
1. Tanda-tanda apa yang terdapat dalam kapata yang disajikan pada saat pelantikan raja Allang di Maluku Tengah ?
2. Bagaimana proses transmisi musik kapata pada kehidupan masyarakat negeri Allang di Kabupaten Maluku Tengah ?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui tanda-tanda apa saja yang terdapat dalam kapata yang disajikan pada saat pelantikan raja Allang di Maluku Tengah.
b. Untuk menjelaskan bagaimana proses transmisi kapata pada masya-rakat negeri Allang.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan sumbangan dan dukungan terhadap upaya pelestarian nyanyian rakyat di Maluku, sebagai konstribusi ilmu pengetahuan, pemicu untuk meningkatkan apresiasi seni musik tradisi Maluku sebagai kekayaan budaya khususnya di kalangan generasi muda dan terutama seniman-seniman musik di Maluku, sekaligus, dalam rangka mengembangkan wawasan kebangsaan yang berdasarkan kepada kearifan lokal.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
Dari hasil pengamatan, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan Kapata atau Nyanyian Tanah masih sangat terbatas jumlahnya. Beberapa pustaka yang berhasil dijumpai telah memberikan sedikit informasi yang berhubungan dengan sejarah dan kebudayaan Maluku. Secara khusus pustaka-pustaka tersebut sedikit menyinggung tentang pengertian Kapata atau Nyanyian Tanah secara umum.
Sejauh ini, informasi tentang kapata ditemui dalam tulisan M C Boulan yang diterjemahkan Saul. J. M. Sijauta tahun 1983, berjudul Uru, Son Of The Sunrise. Dalam tulisan ini menjelaskan tentang bahasa kapata atau bahasa uru, definisi dari kapata, dan berbagai contoh kapata. Pada intinya ditekankan bahwa bahasa kapata atau bahasa uru mengungkapkan peristiwa yang terjadi jauh dalam sejarah manusia.
Dalam tulisan Tamaela tahun 1997, sebuah bunga rampai yang berjudul ”Ekspresi Injil dan Adat dalam Musik Gerejawi di GPM.” Dalam tulisan ini, ia hanya memberikan definisi kapata, yaitu tradisi menuturkan peristiwa dan sejarah masa lampau yang disampaikan secara setengah menyanyi dan setengah berbicara (recitation atau chanting). Selain itu, syairnya dibuat berdasarkan bahasa Tanah atau bahasa daerah setempat dan mengekspresikan cerita-cerita sejarah, nilai-nilai keyakinan, dan cara berinteraksi para leluhur. Selanjutnya, Tamaela menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri kapata, antara lain; tangganada yang umumnya digunakan dalam kapata, yakni tangganada yang terdiri dari dua nada (dwitonic), tiga nada (tritonic), empat nada (heptatonic), dan lima nada (pentatonic), melodi yang bisanya digunakan dalam kapata yaitu satu melodi, cara menya- nyikannya baik secara responsorial style dan antiphonal style, serta alat musik yang mengiringi nyanyian tersebut yaitu tifa dan tahuri (kulit keong laut). Berkenaan dengan permasalahan makna dalam kapata, sama sekali tidak dibahas.
Buku yang berjudul Hikayat Nunusaku ditulis oleh Matulessy, Z M . tahun 1978 diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku. Dalam buku ini, dijelaskan tentang asal mula daerah Maluku, kemudian menjelaskan tentang manusia pertama orang Maluku yang disebut dengan istilah Alifuru yang berasal dari Pulau Seram atau Nusa Ina, dan dalam buku ini sedikit dijelaskan tentang kapata yaitu definisi kapata.
Buku yang berjudul Aneka Ragam Khasanah Budaya Nusantara II yang ditulis oleh Tim Koordinasi Siaran Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1991/1992. Pada halaman 235239 berbicara tentang Kapata, Musik Tradisi Dari Maluku, di mana pada bagian ini dijelaskan tentang bentuk dan jenis kapata.
Dalam buku yang berjudul Kapata: Nyanyian Tradisi di Maluku yang ditulis oleh tim Taman Budaya Provinsi Maluku, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan tentang kapata sebagai nyanyian tradisi, kapata sebagai nyanyian pengiringi tari tradisi, kapata digunakan dalam pesta dan permainan rakyat.
Dalam artikel “Mengenal Siwa-Lima, Mengenal Jatidiri,” Saul Siyauta mencoba mencari arti dari istilah Siwa-Lima dalam kehidupan orang Maluku, di mana dalam sistem kekerabatan orang Maluku khusunya di Maluku Tengah dikenal ada dua kelompok sosial yaitu Pata-Siwa dan Pata-Lima atau kelompok sembilan dan kelompok lima. Dalam tulisan ini juga terdapat ungkapan-ungkapan atau budaya bertutur orang Maluku yang disebut kapata atau nyanyian tanah yang menggunakan bahasa daerah.
B. Landasan Teori
Guna mencari apa arti dari tanda-tanda kapata yang disajikan dalam pelantikan raja Allang di Maluku Tengah sesuai dengan perta-nyaan yang diajukan dalam rumusan masalah , akan digunakan untuk analisis lewat teori semiotika trikotomi dari Charles Sanders Peirce (1839-1914). Langkah awal sebelum sampai pada penelitian semiotika trikotomi, ada baiknya memahami dan mengerti dulu semiotikannya Peirce antara lain; tiga kategori keberadaan yakni, tanda, interpretan, objek, ground dan trikotomi.
Sebuah tanda atau representamen menurut Peirce adalah sesuatu bagi seseorang mewakili yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas.
Menurut Peirce, seperti dikutip Noth (1996:42) “Nothing is a sign unless it is interpreted as sign”. Dengan demikian, sebuah tanda melibatkan proses kognitif di dalam kepala seseorang dan proses itu dapat terjadi jika ada representamen, objek, dan interpretan. Proses semiosis ini sering pula disebut sebagai signifikasi (signification).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gambar 1. Relasi Segitiga Tanda
Dalam proses semiosis seperti pada gambar di atas, akan menghasilkan rangkaian hubungan yang tak berkesudahan, maka pada gilirannya sebuah interpretan akan menjadi representamen, menjadi interpretan lagi, menjadi representamen lagi, dan seterusnya. Proses seperti ini yang tak berujung pangkal oleh Umberto Eco dan Jacques Derrida merumuskannya sebagai proses semiosis tanpa batas (unlimited semiosis) (Budiman, 2003: 26).
Sebagai contoh hasil analisis yang pernah dilakukan sebagai aplikasi dalam penelitian kapata adalah Tangganada yang digunakan dalam lagu Hena Masa Ami adalah pentatonik . Pentatonik adalah tangganada yang terdiri dari lima buah nada, merupakan salah salah satu ciri dari nyanyian rakyat (folksong) di Maluku (Tamaela, 1995: 119). Pada proses semiosis tingkat pertama, penggunaan tangganada pentatonik dalam lagu Hena Masa Ami merupakan representamen yang merujuk pada angka-angka. Selanjutnya, pada proses semiosis representamen yang berikut, angka- angka yang merujuk pada objek salah satu sistem kehi-dupan sosial orang Hulaliu, dalam hal ini orang Ama Rima Hatuhaha. Kelompok Ama Rima Hatuhaha tergolong dalam kelompok Patalima. Patalima adalah satu dari dua kelompok sosial masyarakat yang terdapat di pulau Seram. Kelompok ini dapat diidentifikasi antara lain melalui benda-benda atau simbol-simbol berjumlah lima yang digunakan dalam ritual (Ajawaila, 2000: 17), seperti halnya tergambar dalam nada-nada yang digunakan dalam lagu Hena Masa Ami. Tangganada dalam lagu ini berjumlah lima nada, yaitu nada 2 (re), 2 (ri), 3 (mi), 4 (fa) dan nada 5 (sol).
Sebagai teori pendukung adalah teori Merriam dalam melihat perilaku manusia dan kebudayaannya. Sebagai tingkah laku manusia, musik dapat dihubungkan dengan secara sinkronik dengan tingkah laku lainnya, seperti drama, tari, agama, organisasi sosial, ekonomi, struktur politik, dan aspek-aspek lain (Merriam, 1995 1964: 103). Hal ini mengindikasikan bahwa musik dan aspek-aspek atau tingkah laku lainnya dalam kehidupan manusia memiliki keterkaitan, sehingga pema-haman mengenai suatu kebudayaan tertentu dapat dicapai antara lain lewat studi terhadap musik dalam kebudayaan tersebut. Penggunaan teori ini digunakan untuk mengupas permasalahan transmisi kapata.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gambar 2. Model tiga tahap analisis musik dari Teori Behavior yang dikemukakan Alan P. Merriam. Musik sebagai bunyi, atau musik yang dimainkan, dipengaruhi oleh konsep yang ada pada masyarakat pemilik musik, dimana konsep tersebut kemudian akan berpengaruh pada perilaku masyarat dalam bermusik. Sumber: Alan P. Merriam, 1964.
Fenomena ini dapat dipahami lewat teori yang dikemukakan oleh Alan P. Merriam dalam bukunya yang berjudul The Anthropology of Music (1964), seperti yang digambarkan dalam bentuk bagan di atas. Ia menyarankan tiga tahapan dalam analisis musik. Tiga tahapan tersebut meliputi (1) conceptualization about music, (2) behaviour in relation to music, dan (3) music sound itself (1964:32). Selanjutnya, menurut Merriam, “...there is a constant feedback from the product to the concepts about music, and this is what accounts both for change and stability in music system” (1964:33). Model ini membentuk sebuah siklus, dimana konsep mempengaruhi perilaku yang menghasilkan bunyi. Ada umpan balik yang konstan dari produk terhadap konsep musik.
C. Sekilas tentang Kebudayaan Negeri Allang
1. Asal-usul Penduduk dan Sejarah Terbentukya Negeri Allang
Negeri Alang adalah sebuah negeri yang terdapat di jazirah Leihitu pulau Ambon pada pintu masuk teluk Ambon. Menurut sumber sejarah lisan yang dituturkan oleh orang-orang Alang, menuturkan bahwa datuk- datuk mereka berasal dari pulau Seram (Hoaumaol), pulau Jawa, pulau Tidore dan pulau Ternate, pulau Bacan dan pulau Obi di Maluku Utara.
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta.
Gambar 3. Peta Pulau Ambon dan letak negri Allang, yang ditandai dengan lingkaran merah (Sumber: www.google.com)
Mengenai kedatangan datuk-datuk orang Allang ke pulau Ambon seperti digambarkan di atas, dapatlah dikategorikan dalam dua kelompok besar. Imigran pertama ke pulau Ambon adalah orang-orang Alifuru (penduduk asli: alif artinya awal dan uru artinya manusia) di Seram barat (Nunusaku) yang tediri dari marga Ralahalu seorang tokoh atau pemimpin, Halawane, Lalihatu, Mauwa mereka meninggalkan tempat tinggalnya mencari tempat baru yang lebih aman. Kelima keluarga besar kemudian sepakat mengadakan perjalanan ke selatan untuk mencari tempat yang lebih aman dan subur dipimpin kapitan Ralahalu dengan memakai gosepa (rakit) mereka tiba di tanah Hitu (negeri Hitu).
Namun mereka ditolak dan selanjutnya menuju ke daerah perbatasan antara Negeri Lima dan Wakal. Di sini mereka bertemu dengan tiga orang bersaudara dari Negeri Lima yaitu: (1) Tau Ki; (2) Tau Ka; (3) Hiti Putih Ehu (Siti Ehuputik), seorang perempuan. Perjalanan diteruskan ke pegunungan dan di sana dimusyarawahkan suatu perjan-jian mengenai batas tanah antara ketiga keluarga dari Seram itu ke negeri Allang. Di hutan pegunungan Allang itu mereka mendirikan tujuh buah Hena yaitu: (1) Hinamutua; (2) Heiua Suing; (3) Hinatueng; (4) Hiaowolit; (5) Huiaanou; (6) Neinamale; dan (7) Henaitu. Henaitu dijadikan pusat kekuasaan adat dan Ralahalu sebagai pemimpin kemudian menetapkan Lelehatu sebagai kapitan dan Tuan tanah yang kemudian dikenal sebagai pemimpin Lumahtau (rumahtau) Lalihatu. Hena-hena tersebut di atas dianggap orang- orang Allang sebagai bekas Negeri lama mereka juga. Penduduk ini dianggap sebagai orang asli Allang. Dengan kedatangan warga-warga pendatang antara lain: (1) Sabandar; (2) Siwalette; (3) Huwae; (4) Nussy, yang dipimpin oleh kapitan Sabandar (Maheri) dapat dibuat suatu perdamaian dengan orang-orang Alifuru di Hinaitu untuk turun ke negeri Allang sekarang.
Rombongan kedua orang-orang Alifuru dari Seram sekitar abad ke- 15 adalah Sipakoly, Mauhwa dan Lopulua. Kedatangan ketiga marga ini bersama dengan para pendatang dari Maluku Utara. Imigran orang-orang atau warga dari Maluku utara dapat dicatat antara lain dari Tidore, Ternate, Halmahera, Bacan, Obi dan pulau Jawa. Mereka dikenal sebagai Sembilan keluarga atau Patasiwa Allane, yang sebelumnya telah menetap di pulau Bacan Maluku Utara. Kesembilan keluarga/warga yang sudah sepakat yaitu: (1) Sabandar; (2) Laumahu; (3) Nussy; dan (4) Patty yang datang dari Tidore dan Ternate bersama dengan warga (5) Huwae; (6) Pelasula; (7) Lopumetten, (8) Pelahula dan (9) Siwalette yang datang dari Bacan dan Obi.
Sebelum keberangkatan dari Maluku Utara mereka bersumpah untuk bersatu. Sumpah itu disebut Kahori yang mempunyai arti bahwa tidak ada perbedaan dalam derajat hidup Sembilan keluarga adalah satu keluarga seibu sebapak, hidup saling mengasihi, bersatu, dan berjuang melawan setiap ancaman dengan semangat pantang mundur. Walau terpisah-pisah dalam perjalanan, namun tetap berusah untuk kembali dengan air sumpahan yang telah diminum dan ikrar bersama semangat Kahori. Proses pencarian negeri yang baru dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain hingga akhirnya mereka tiba disuuatu tempat yang diberi nama Namana yang berarti Berhenti. Disebut pula dengan nama Allang Lama.
Penduduk asli Alifuru ini seperti dijelaskan sebelumnya telah membangun tujuh buah Hena. Namun dengan bijaksana para pemimpin dari kaum pendatang mempersatukan penduduk asli itu dengan mereka dan bersama-sama berdiam di Namana. Tetapi di tempat ini sering terjadi musibah karena banjir sungai yang menghanyutkan anak-anak, dan sering juga dimangsa buaya. Mereka kemudian bersepakat untuk mencari tempat pemukiman yang lebih baik. Akhirnya, mereka mene-mukan suatu tempat yang dianggap baik dan dijadikan sebagai pusat negeri Allang. Nama Negeri yang dibangun disebut Allane yang mengandung arti “Allah telah menolong, melindungi dan telah mem-bungkus”. Secara harfiah kata ini terdiri dari “Al” dan “Lama”. Al itulah “Allah” dan “Lama” itulah pertolongan atau perlindungan (Pattikayhatu, 2003).
2. Kehidupan Budaya Masyarakat Allang
a. Sistem Kepercayaan
Kepercayaan masyarakat negeri Allang pada dasarnya sama dengan kehidupan masyarakat Maluku pada umumnya. Seperti dijelas-kan dalam buku Sejarah Daerah Maluku (Pattikayhatu, 1993) masyarakat Maluku memiliki kepercayaan yang berkisar pada alam atau kekuatan gaib dan dunia kematian. Lebih jelasnya kepercayaan kepada alam dan sebagiannya baru mencapai bentuk yang nyata pada zaman Neolitikum dan di zaman Perunggu-besi, yaitu pada saat masyarakat mengenal kehidupan mentetap dan bercocok tanam dengan suatu susunan pemerintahan semacam perkampungan.
Hidup bercocok tanam lebih mendekatkan manusia kepada hidup berkepercayaan. Para petani selalu mengharapkan roh-roh gaib selalu memberikan restu dan kesuburan. Ilmu perbintangan juga merupakan bukti bahwa adanya suatu kepercayaan. Selain itu kapak-kapak maupun nekara-nekara yang terbuat dari batu dan perunggu menunjukkan akan adanya berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam upacara-upacara yang tentunya berhubungan erta dengan kepercayaan. Selain itu ada juga bangunan-bangunan seperti tiang batu, meja batu kubur, batu memberi kesan bahwa pemujaan roh kepada nenek moyang mengambil peran penting dalam kehidupan kerohanian pada waktu itu.
b. Sistem Kekerabatan
Orang Allang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu suatu sistem dimana hubungan-hubungan kekerabatan seseorang ditentukan menurut garis keturunan. Ayah (bapak) dan kerabat laki-laki. Dalam sistem ini anak laki-laki merupakan penerus keturunan, sedangkan anak perempuan merupakan anggota kekerabatan sebelum dia menikah. Menurut sistem, yang menjadi anggota kekerabatan hanyalah kakek dan nenek dari pihak ayah di samping saudara laki-laki dari pihak ayah berikut anak-anaknya.
c. Upacara Ritual di Negeri Allang
1) . Upacara Perkawinan
Sistem perkawinan yang berlaku di Negeri Allang dilakukan melalui masuk minta disamping itu, orang Allang juga menganut sistem masuk manua dan kawin lari meskipun pada prinsipnya kurang dihormati. Sistem masuk minta, yaitu sistem dimana keluarga pacar laki-laki masuk minta pacar perempuan dari orang tua dan keluarganya. Apabila pinangan disepakati, kedua belah pihak langsung menentukan waktu pernikahan dan kain tampa atau arat (mas kawin). Kain tampa ini biasanya diantar oleh keluarga calon mempelai laki-laki keluarga kecalon mempelai perempuan sehari sebelum dilangsungkannya upacara pernikahan. Besarnya kain tampa tergantung rumatau, sementara jumlah hartanya selalu dibayar bedasarkan angka simbolik 7 (tujuh) atau 9 (sembilan).
Jenis barang atau harta selalu mempunyai hubungan dengan peristiwa kelahiran. Ada kain merah dan barang melambangkan darah pada saat melahirkan, ada kain putih melambangkan pakian bayi yang disipsikan, ada juga minuman keras melambangkan kesiapan bapak menunggu kedatangannya sang bayi sambil minum minuman keras, ada juga tempat sirih, yang melambangkan kesiapan kaum ibu dalam menjeput kelahirannya sang bayi dimuka bumi sambil memakan sirih pinang. Menurut pemangku adat di Negeri Allang kain tampa ini seolah-olah memiliki kekuatan magis yang tinggi. Jika tidak dipenuhi, maka akan ada resikonya, entah kematian anak, tidak mendapat keturunan atau resiko dan musibah lainnya. Mereka mengatakan bahwa para leluhur telah menetapkan ketentuan-ketentuan ini dengan sumpah, sehingga barang siapa yang melanggaranya harus bertanggung jawab kepada Upu lanite.
Sistem masuk minta, yaitu sistem di mana pacar laki-laki bebas masuk keluar rumah pacar perempuan, meskipun belum ada persetujuan dari kedua belah pihak. Sedangkan sistem kawin lari dilakukan secara terpaksa, karena keluarga dari pihak keluarga perempuan tidak menye-tujui hubungan anaknya dengan laki-laki.
2) . Upacara Panas Pela
Upacara panas pela merupakan suatu upacara adat untuk mempe- ringati peristiwa awal terjadinya suatu ikatan atau perjanjian pela antara masyarakat dua negeri, baik yang beragama Islam dan Kristen, juga beragama Kristen dan Kristen. Tujuan dari kegiatan panas pela selain untuk memperingati kembali awal terjadinya pela, juga untuk saling membangkitkan semangat cinta kasih masyarakat dari kedua negeri itu untuk lebih memupuk, mempererat, meningkatkan rasa persaudaraan dan persekutuan hidup masyarakat mereka.
Pela adalah suatu bentuk ikatan persaudaran atau suatu perjanjian yang dilakukan antara dua negeri dimana masyarakatnya wajib hidup saling mengasihi dalam satu persekutuan persaudaraan, saling menolong didalam aspek kehidupan bersaudara. Hubungan pela antar kedua negeri itu terjadi karena saling mempunyai kepentingan ditinjau dari segi sosial, ekonomi dan politik yang diwujudkan dalam kebutuhan saling membu- tuhkan. Kebutuhan itu antara lain kebutuhan pembangunan rumah-rumah ibadat, mesjid, gereja, kebutuhan rumah tangga yang diwujudkan dengan kawin-mawin dan kebutuhan menghadapi gangguan keamanan yang datang dari luar.
Negeri Allang dengan penduduk beragama Kristen memiliki hubungan pela dengan negeri Lima dengan penduduk bergama Islam. Kedua negeri ini mempunyai hubungan layaknya adik-kakak, karena pengaruh dan peran keluarga melalui Sitti Ehuptih dan Negri Lima, yang kemudian menjadi negeri penduduk Allang. Mereka yang dimaksud adalah keluarga yang di Negeri Allang terkenal dengan nama Lomata Sipahelut yang menurut cerita orang Allang, berasal dari Hena Latua, namun menurut sumber dari Negri Lima, mereka ini berasal dari Nau. Di Nau keluarga ini di kenal dengan nama Lulihelut
Hubungan persaudaraan antara Negeri Allang dan Negeri Lima merupakan salah satu contoh hubungan antara Negeri atau Hena yang berbeda agama tetapi kokoh dan penuh semangat kekeluargaan. Semangat itu kemudian menjadi dasar diberlakuakannya ketentuan bagi orang Allang yang datang ke Negeri Lama, akan memperoleh semacam hak untuk memetik berbagai macam buah-buahan hasil tanaman penduduk yang disukainya. Selama pangkuku (Jolok) yang digunakan mencapai buah- buahan tersebut, begitu pula sebaliknya berlaku bagi orang Negeri Lima yang datang ke Negeri Allang.
Hubungan antara Negeri Allang dengan Negeri Latuhalat adalah hubungan pela, dimana hubungan ini terjadi sekitar akhir abat ke-16. ketika acara perkawinan antara Petrus Huwae dari negeri Allang dengan Constanza Lekatompessy dari negeri Latuhalat. Hubungan ini merupakan hubungan persaudaraan kedua negeri yang menganut kepercayaan yang sama, yaitu agama Kristen. Ikatan ini disebut pela batu karang, kesepakatan pela ini dikokohkan dengan sumpah atas nama Upu Lanite dengan ketentuan orang Allang tidak boleh menikah dengan orang Latuhalat dan sebaliknya.
3) . Upacara Pelantikan Raja
Raja adalah pemimpin di sebuah negeri atau desa. Pengangkatan seorang pemimpin negeri di Maluku pada awalnya berdasarkan garis keturunan tanpa melalui pemilihan masyarakat yang penting telah disetujui oleh para tua-tua adat dalam saniri negeri. Dengan adanya peraturan daerah maka sistem pengangkatan raja pun mulai mengalami perubahan, seperti terjadi pada zaman sekarang ini. Pengangkatan raja sekarang ini pada dasarnya juga dari garis keturunan, bagi masayarakat sebuah negeri yang merupakan garis keturunan raja punya hak untuk mencalonkan diri sebagai raja, lebih jelasnya sangat demokratis. Setelah disetujui oleh saniri negeri beberapa calon raja itu harus dipilih oleh masyarakat negeri tersebut melalui proses pemilihan langsung, dan dari sekian calon itu yang memiliki suara terbanyak dialah yang dinobatkan sebagai raja dari negeri tersebut. Dengan terpilihnya seorang raja lewat prosedur yang dijelaskan di atas, selanjutnya akan diadakan pelantikan raja sebagai wujud pengakuan masyarakat dan pemerintah. Kegiatan inilah yang disebut upacara pelantikan raja, hal inipun berlaku bagi negeri Allang.
Di negeri Allang upacara pelantikan raja dilakukan pada hari yang telah disetujui oleh tua-tua adat. Menurut sumber sejarah lisan bagi masyarakat Allang hari yang baik untuk melakukan sebuah kegiatan ritual di negeri tersebut biasanya dilakukan pada hari selasa dan jumat. Setelah ditentukan waktu pelaksanaan pelantikan raja, selanjutnya panitia kegiatan tersebut melakukan rencana pelaksanaannya yang disetujui oleh pihak pemerintah dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Maluku Tengah.
Proses pelantikan raja Allang seperti diungkapkan oleh skretaris negeri Allang sesuai hasil wawancara tanggal 15 Mei 2011 terbagi atas tiga bahagian yaitu; pelantikan adat berlangsung di rumah adat atau baeleo, pengukuhan di rumah gereja dan penobatan oleh kepala adat dirumah perintah.
BAB III METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan etnomusikologi. Pendekatan etnomusikologi digunakan ber- dasarkan prisnsip kerja etnomusikologi seperti yang diungkapkan oleh Seeger (1982: vi), yakni mengkaji musik, tidak hanya musik itu sendiri, melainkan juga dalam kaitannya dengan konteks budayanya. Pemilihan pendekatan etnomusikologi ini terutama digunakan untuk mengum- pulkan data-data, selanjutnya data-data itu akan di anilisis dengan Teori semiotika trikotomi dari Peirce sebagai pisau bedah untuk menjawab permasalahan pertama yaitu menggali makna dari tanda-tanda pada kapata. Untuk menjawab permasalahan kedua akan digunakan teori Behavior yang dikemukakan Alan P. Merriam tentang tiga tahap analisis musik.
B. Pemilihan Sampel
Istilah kapata biasanya digunakan di daerah Maluku Tengah, sehingga sampel yang digunakan adalah kapata yang berada masyarakat negri /desa yang berada di wilayah Maluku Tengah sesuai dengan pertanyaan penelitian yaitu Pulau Ambon negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Untuk pemilihan sampel utama dalam penelitian ini adalah kapata-kapata yang sering digunakan oleh masyarakat setempat dalam kegiatan ritual pelantikan raja ada di daerah tersebut.
Pemilihan sampel ini berdasarkan kenyataan dan data-data yang diperoleh, seperti negeri Allang, masyarakat di negeri ini masih memper- gunakan kapata-kapata dalam setiap kegiatan ritual adat. Di negeri ini juga dalam kehidupan sehari-harinya masih mengunakan bahasa tanah atau bahasa daerah. Kenyataan seperti ini berbeda dengan negeri-negeri lain yang berada di kawasan Pulau Ambon, yang sering menggunakan bahasa Melayu Ambon dalam kehidupan mereka. Bahasa tanah hanya digunakan pada saat-saat tertentu saja, seperti pelaksanaan acara ritual, itupun digunakan oleh orang-orang yang dianggap penting dalam desa bersang- kutan seperti, pemangku adat atau tokoh-tokoh adat setempat.
C. Tahap Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut.
1. Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang kapata. Sebelum melakukan wawancara adalah melakukan pengamatan setelah tiba ditempat penelitian, pengamatan yang dilakukan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi lokasi peneltian secara menyeluruh. Setelah melakukan pengamatan adalah mencari informan, pencarian informan didasarkan pada pemahaman mereka tentang objek yang diteliti, mudah di ajak bicara, dengan senang hati memberikan informasi dan bahkan mau menerima informasi dari peneliti, yakni para pelaku atau penyaji dan penonton atau masyarakat. Wawancara kepada informan yang bertindak sebagai penyaji terutama digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang syair dan melodi dari kapata, sedangkan wawancara terhadap informan penonton digu-nakan untuk mengumpulkan informasi terutama tentang pandangan masyarakat terhadap kapata pelantikan raja. Setelah mendapatkan para informan, selanjutnya akan dilakukan wawancara. Wawancara pada dasarnya adalah proses interaksi antara individu yang bertindak dalam status yang sama, “yang diteliti” tidak lagi dilihat sebagai ‘the other’. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang bertipe wawancara terstruktur dan tidak ada pembatasan kuantitas informan, sebab yang dibutuhkan ialah data jenuh. Tetapi, sebelum melakukan wawacara terstrukur, terlebih dahulu dicari informasi mengenai kebiasaan-kebiasaan para informan. Hasil data wawancara merupakan catatan dalam bentuk tulisan bahkan lewat perekaman. Data wawan- cara itu lebih terfokus untuk menjawab permasalahan kedua tentang transmisi kapata. Salah satu hasil wawancara untuk menjawab permasalahan pertama adalah dengan mewancarai salah satu informan yang dianggap baik dalam memberikan data kepada penulis tentang sampel utama yaitu kapata pelantikan raja, yaitu P Huwae (Mei 2011). Dalam wawancara tersebut P Huwae memberikan penjelasan tentang kapata pelantikan raja sekaligus mendengarkan kapata yang dinyanyikannya, dan dilanjutkan dengan pentranskripsian. Transkripsi yang digunakan di sini adalah transkripsi dari visual dibuat kedalam notasi. Jadi, notasi yang disajikan dan digunakan sebagai bahan analisis dalam menjawab permasalahan kedua setelah membandingkannya dengan data doku- mentasi.
2. Dokumentasi (audio-visual) merupakan metode pengumpalan data yang dianggap penting, sebab penelitian terhadap kapata yang disajikan dalam pelantikan raja dilaksanakan pada saat tertentu saja. Guna men- dapatkan data tentang kapata itu, rekaman yang digunakan adalah hasil rekaman pada saat acara pelantikan raja tahun 2006. Tapi, sebagai bahan pembanding peneliti melakukan perekaman ulang terhadap informan meskipun tidak dalam konteks pelantikan raja. Hasil rekaman baik acara pelantikan raja maupun rekaman pembanding merupakan langkah awal untuk melakukan anlisis semiotika guna mencari arti dari tanda-tanda pada kapata, dengan cara setelah mendengarkan hasil rekaman kemudian mentranskripsinya dalam bentuk notasi, kemudian hasil tersebut di analisis dan dideskripsikan.
3. Studi pustaka digunakan dalam dua tahap, yaitu sebelum melakukan penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang objek penelitian, baik itu sejarah tentang Musik di Maluku dalam hal ini adalah kapata dan sejarah Negeri Allang, teori apa saja yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, serta memperdalam metode. Kemudian untuk mendapatkan pustaka-pustaka tentang objek penelitian yaitu kapata, maka cara yang dilakukan adalah dengan cara mengunjungi beberapa perpustakan, pustaka-pustaka yang diberikan dari teman, bahkan dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari internet. Selain itu, studi pustaka juga digunakan sebagai bahan untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan sekaligus juga di- fungsikan sebagai teknik triangulasi, yakni pembanding bagi data wawancara dan pengamatan, kemudian mendiskripsikannya. Studi pustaka ini lakukan pada saat selesai melakukan penelitian.
D. Metode Analisis Data
Setelah mendapatkan data-data dari wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, maka akan dilakukan analisis data. Seperti yang telah dikemukakan terdahulu, untuk mencari tanda-tanda apa saja yang ada dalam kapata akan digunakan teori trikotomi dari Peirce.
Data-data tersebut akan dianalisis dengan semiotika trikotomi yaitu representament, objek, interpretant. Sebagai contoh, representament adalah delapan buah nada yang digunakan dalam kapata apabila dihubungkan dengan objek kelompok soa yang berjumlah delapan soa. Selanjutnya, representament tersebut dihubungkan dengan interpretant, untuk menghasilkan makna dari tanda-tanda pada kapata.
Untuk menjawab permasalahan kedua tentang proses transmisi, maka hasil data dari wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini di analisis lewat teori Alan P Merriam tentang tiga tahapan analisis musik, yakni konsep, perilaku dan bunyi musik. Musik sebagai bunyi dalam hal ini kapata, atau musik yang dimainkan, dipengaruhi oleh konsep yang ada pada masyarakat pemilik musik, dimana konsep tersebut kemudian akan berpengaruh pada perilaku masyarat dalam bermusik. Keterkaitan antara bunyi musik, perilaku dan konsep akan berlangsung seterusnya.
E. Hasil Pengumpulan Data
1. Musik di Maluku
Maluku memiliki budaya musik yang beragam, yang masing- masing memiliki keunikan, sebagai hasil dari sintesis kreatif antara tradisi- tradisi lokal dengan pengaruh yang datang dari luar. Banyak bentuk musikal berkaitan dengan praktek-praktek religious, termasuk musik gereja yang dipengaruhi oleh gaya Kristen-Eropa, musik yang dipengaruhi oleh budaya Islam-Timur Tengah, dan musik-musik yang lekat dengan pemujaan leluhur dan roh-roh dalam kepercayaan lokal.
Maluku Utara didominasi oleh penduduk yang memeluk agama Islam, sedangkan Maluku (yakni tengah dan selatan) didominasi oleh penduduk yang beragama Kristen. Agama Islam masuk ke Maluku pada abad ke-15, dan kini banyak dijumpai kantong-kantong pemukiman penduduk Muslim di wilayah Maluku Tengah dan Tenggara. Seiring dengan kedatangan Portugis pada tahun 1512, para penduduk yang tidak memeluk Islam beralih memeluk agama Katolik dan mulai memprak- tekkan musik gereja Katolik-Portugis.
Musik gereja Katolik cukup berpengaruh hingga datangnya Belanda pada tahun 1605, sehingga Ambon dan wilayah-wilayah sekitar-nya mulai dipengaruhi oleh kebudayaan Belanda, serta sebagian besar masyarakatnya mulai beralih memeluk agama Kristen. Saat ini, sebagian besar penduduk Maluku beragama Kristen Protestan, meski ada pula jumlah pemeluk Katolik yang substansial, terutama di wilayah Kei dan Tanimbar. Kendatipun demikian, seni-seni pertunjukan yang menjadi mainstream terutama berangkat dari keyakinan-keyakinan lokal, yakni yang berkaitan erat dengan pemujaan leluhur dan roh-roh, misalnya, yang sangat menonjol ialah kapata. Lagu-lagu rakyat Maluku masih sangat populer sampai saat ini.
a. Pengaruh Musik Timur Tengah
Maluku, seperti halnya sebagian besar wilayah Indonesia lainnya, telah mengalami berbagai interaksi dengan budaya-budaya luar semenjak beberapa abad silam. Kedatangan para bangsa asing ke Indonesia, termasuk ke Maluku, setidaknya dilatarbelakangi oleh tiga alasan dan tujuan, yakni mencari wilayah yang memiliki sumber daya alam yang bagus, untuk kemudian dieksploitasi dan diperdagangkan, menyebarkan agama, dan mencari daerah jajahan atau koloni. Alasan dan tujuan ini dikemukakan secara eksplisit oleh VOC sebagai tujuan kerja mereka, yakni gold, gospel, dan glory.
Kurang lebih seabad sebelum kedatangan bangsa Barat ke Maluku, para musafir dari Timur tengah telah menginjakkan kakinya di wilayah ini, khususnya dengan maksud berdagang, dan sedikit diselubungi dengan tujuan-tujuan penyebaran agama Islam. Dampak serta sisa-sisa yang ditimbulkan oleh kedatangan orang-orang dari Timur Tengah di maluku misalnya terlihat pada musik sawat dan hadrat. Musik sawat dan
hadrat cukup kental dengan karakter musikal yang sejauh ini seringkali diasosiasikan dengan musik ‘Islami’, misalnya penggunaan instrumen rebana (jenis frame drum), syair-syair yang berbahasa Arab, dan peng- gunaan modus-modus minor-zigana dalam pola-pola melodi yang dimainkan oleh seruling. Musik sawat dan hadrat lahir dan berkembang terutama di kantong-kantong pemukiman berpenduduk muslim.
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta.
Gambar 4. Musik sawat, salah satu pengaruh musik Timur Tengah di Maluku (Sumber: www. google.com, 2011)
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta.
Gambar 5. Musik hadrat, juga merupakan salah satu pengaruh musik Timur Tengah di Maluku (Sumber: www. google.com, 2011)
b. Pengaruh Musik Eropa
Penyebaran musik Barat di Maluku diperkirakan sekitar awal abad ke-16, bersamaan dengan kedatangan bangsa Portugis dalam rangka perdagangan rempah-rempah dan penyebaran injil. Musik Gregorian merupakan musik Barat pertama yang dikenal oleh masyarakat Maluku , khususnya di daerah Maluku Utara, dari kontak mereka dengan bangsa Barat. Musik ini kemudian menyebar ke seluruh Maluku, termasuk Ambon. Musik-musik Gregorian sering digunakan dalam kegiatan ke- agamaan di gereja (Bramantyo, 2004: 31-93).
Dari segi instrumen, pengaruh musik barat di Maluku terlihat dari ditemukannya dua macam biola di pulau Buru, yang masing-masing menggunakan tiga senar dan berbeda ukuran. Alat musik ini, menurut salah seorang penulis asing yang bernama Claartje Gieben, diduga berasal dari bangsa Portugis yang disebut vihola di Buru (Gieben at all dalam Bramantyo, 2004: 94). Selain itu, ada juga musik keroncong yang dibawa oleh bangsa Portugis ke Maluku.
Selain bangsa Portugis, orang-orang Belanda juga memiliki penga- ruh terhadap kehidupan musik di Maluku. Mereka turut berperan dalam mengembangkan sistem tangga nada diatonik di wilayah ini. Salah seorang misionaris asal Belanda, yaitu Yoseph Kham, memperkenalkan suling bambu horizontal dalam kegiatan pelayan ibadah di Gereja, untuk mengiringi nyanyian jemaat.
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta.
Gambar 6. Suling bambu, salah satu pengaruh musik Eropa di Maluku, yang menggunakan tangganada diatonik (Sumber: www.google.com, 2011)
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta.
Gambar 7. Suling bass dalam ansambel suling bambu di Maluku, biasa digunakan dalam ibadah di gereja (Sumber: www.google.com, 2011)
c. Musik Asli Maluku
Musik asli di Maluku dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu musik tradisi di Maluku dan musik tradisi Maluku. Musik tradisi Maluku merupakan musik yang telah mengalami sebuah proses alkulturasi budaya dengan bangsa dan daerah yang lain. Akan tetapi, musik ini masih kuat dengan karakteristik lokal, seperti musik totobuang, hawaian, sawat, jukulele (khusus untuk lagu seperti lagu-lagu yang berirama hawaian). Musik tradisi di Maluku merupakan musik yang lahir dan berkembang di wilayah ini tanpa, ada pengaruh-pengaruh luar. Sebagai contoh ialah tifa, tahuri (kulit keong laut) dan musik vokal seperti kapata. Musik-musik ini masih berkembang sampai saat ini.
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta.
Gambar 8. Musik totobuang, salah satu musik tradisi Maluku (Sumber: www.google.com, 2011)
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta.
Gambar 9. Musik tahuri, salah satu musik tradisi di Maluku (Sumber: www.google.com, 2011)
Masyarakat Maluku pada umumnya masih taat pada petuah-petuah yang diberikan oleh para leluhur mereka melalui kapata-kapata yang disampaikan. Sebagai contoh salah satu kapata “ Sei hale hatu, hatu lisa pei. Sei lei sou, sou lesi ei “ terjemahan bahasa Ambon Malayu “Siapa bale batu, batu gepe dia. Siapa langgar sumpah, sumpah bunuh dia” terjemahan bebas “Siapa membalik batu, maka batu itu akan menindihnya. Siapa melanggar sumpah yang di amanatkan oleh para leluhur, maka ia akan mendapatkan malapetaka.“ Menurut sejarah lisan malapetaka ini dapat berupa hukuman mati bagi pelanggarnya. Tidak ada orang yang tahu kapan dan oleh siapa kapata-kapata ini diciptakan, kapata ini telah ada waktu orang-orang asing yang pertama kali datang ke Maluku yaitu bangsa Portugis (Tim
Koordinasi Siaran Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1991/1992: 235).
1) . Pengertian Kapata
Di dalam tradisi Siwa Lima, kapata terdiri dari tiga kata, yakni Kapa, Pata dan Tita. Kapa adalah Puncak gunung yang berbentuk tajam seperti jari telunjuk yang menujuk ke langit. Pata berarti diputuskan, definitif, tak dapat diubah. Tita adalah sabda, ucapan tegas. Dengan demikian, Kapa Pata Tita berarti ucapan-ucapan tegas tak dapat diubah, yang naik keatas sebagai gunung berpucuk tombak tertuju ke Allah. Atau, dengan kata lain, kapata adalah ucapan-ucapan yang suci dan yang mempunyai kekuatan (Matulessy , Z M 1978: 30; Boland, M.C 1983: 28; Siyauta Saul, 1986). Sedikit berbeda dengan pengertian di atas, Christian Tamaela (1997) mendefinisikan kapata sebagai tradisi menuturkan peristiwa dan sejarah masa lampau yang disampaikan secara setengah menyanyi dan setengah berbicara (recitation atau chanting).
2) . Fungsi Kapata
Bagi masyarakat Maluku, musik sangat penting bagi kehidupan mereka, khususnya dalam upacara-upacara ritual. Ini disebabkan karena musik dapat menghubungkan mereka dengan penguasa alam lewat ungkapan-ungkapan rasa senang atas keberhasilan, kegembiraan karena kedatangan tamu, rasa sedih dan susah atas kematian, rasa indah yang dilihat dan didengar dari lingkungan.
Alan P. Merriam, dalam bukunya yang berjudul The Anthropology of Music, menyebutkan ada sepuluh fungsi musik, yaitu: (1) sebagai pe- ngungkapan emosional (the function of emotional expression); (2) Sebagai kepuasan estetis (the function of aesthetic enjoyment); (3) sebagai hiburan (the function of entertainment), (4) sebagai sarana komunikasi (the function communication), (5) sebagai representasi simbolis (the function symbolic representation), (6) sebagai respon fisik (the function of physical representation), (7) sebagai penguat keserasian norma-norma sosial (the function of enforcing conformity to social norms), (8) sebagai pengesah institusi sosial dan upacara ritual keagamaan (the function of validation social institution and religious rituals), (9) sebagai sarana penunjang kelangsungan dan stabilitas kebudayaan (the function of contribution to the continuity and stability of culture), (10) sebagai penunjang intergritas masyarakat (the function of contribution to the intergration of society) (Merriam, 1964: 219-227).
Apabila dihubungkan dengan musik kapata, fungsi musik yang dikemukakan oleh Merriam di atas masih relevan, ini bisa terlihat lewat syair dari kapata-kapata yang ada di Maluku. Kapata antara lain berfungsi sebagai pengungkapan emosional, sebagai representasi simbolis, sebagai penunjang keserasian norma-norma kemasyarakatan, sebagai sarana komunikasi, sebagai pengesah institusi sosial, dan sebagai penunjang intergritas kemasyarakatan
3) . Jenis-jenis Kapata
a) . Kapata Hasurite
Kapata ini dipergunakan untuk tata upacara resmi seperti peres-mian anak negri, bangunan negri, penghormatan tamu agung dan upacara lain yang setingkat dengannya. Liriknya berisi petuah para leluhur, peraturan adat dan pandangan kehidupan masyarakat serta harapan-harapan yang didambakan oleh masyarakat banyak. Sistem nada yang digunakan adalah empat buah nada yang terdiri dari do, re, fa dan la. Berikut ini adalah contoh kapata hasurite.
Upu ama karo pela, karo pela, ooooh
Tana sena hari hatu, hari hatu.
Hari hatu nesi pemu, ooooh
Amako, amako.
Terjemahan bebas: Ingatlah apa yang telah di amanatkan oleh para datu janganlah dirubah lagi. Barang siapa merubah amanat itu akan tertimpa dan terlindas malapetaka.
b) . Kapata Mako-mako
Kapata ini digunakan untuk memanjatkan doa seperti pengucapan syukur, menyampaikan hajat, menggalang tekad atau selamatan untuk hasil yang telah dicapai dalam usaha. Isi liriknya pada umumnya berupa pujian yang mengangungkan Tuhan, kebesaran negri atau kebesaran kepala negri atau pahlawan yang dianggap berjasa kepada masyarakat. Sistem nada yang digunakan adalah empat buah nada, seperti dalam kapata hasurite. Bentuk syairnya seperti berikut:
Yana siwa rio saka mano mese,
Yana siwa rio saka mano mese,
Puti malalawa hai ria siri oooh,
Puti malalawa hai ria siri oooh,
Sin sin tatasin wame momo,
Sin sin tatasin wame momo,
Momo jane hua hua kira kira oooh,
Momo jane hua hua kira kira oooh,
One mana one roti sampa kalo
One mana one roti sampa kalo
Babu lua, batu lua roti sampa kalo
Babu lua, batu lua roti sampa kalo
Terjemahan bebas: Hai orang Siwa Lima jaga negerimu, waspada difajar menyingsing, jangan sampai diserang musuh. Hai orang muda rapatkan barisan, dengan penuh semangat siaga. Orang tua berdoa, mengatur siasat, sambil makan sirih dan pinang, supaya tidak mengantuk.
c) . Kapata Cakalele
Kapata ini digunakan untuk upacara persiapan perang, menggalang persatuan atau menyambut kemenangan para pahlawan negri. Isi dari lirik kapata cakalele bernafaskan petuah dan amanat leluhur, peringatan dan anjuran sebagai gemblengan moral kaum muda atau mitos kepahlawanan. Nyanyian dan tari cakalele ini biasanya dilakukan pada malam hari dengan buaian api unggun semalam suntuk serta minum arak sebagai penghangat suasana. Bentuk syair ini sebagai berikut.
Hei lete, hei lete, Nunusaku ooh, Nunusaku ooh,
Tui, Tui hei lete, hei lete, Nunusaku ooh.
Kuako rimu rina Nusa, Rimu rina Nusa ooh
Rimu rina wake, Kena mata ooh
Terjemahan bebas: Hei rakyat Nunusaku, ayo turun, ayo turun dari Nunusaku. Tanjung Kualo berair jernih, tenang, teduh. Sejernih dan setenag pikiran kita, dan seteduh batin kita serta iman, Cuma memperkokoh kemenangan dan keberhasilan.
Tempo dari masing-masing jenis kapata satu sama lain berbeda, yang kemudian menjadi ciri dari masing-masing kapata. Contohnya, kapata hasurite pada umunya lambat, berat dan bersifat magis. Kapata mako-mako mempunyai beberapa macam tempo: mula-mula dengan tempo sedang, kemudian makin cepat, hingga cepat sekali, dan kemudian kembali ke tempo semula. Cara menyanyikan dengan tempo seperti ini diulangi sampai empat kali putaran, dan setelah itu disambung dengan beristirahat. Pada kapata cakalele, sesuai makna dan maksud kapata ini, sejak awal temponya sudah cepat makin lama makin cepat sampai cepat sekali.
BAB IV PEMBAHASAN
A. Makna Tanda Kapata yang disajikan dalam Pelantikan Raja Allang
1. Kapata Dalam Pelantikan Raja Allang
a. Vokal dan Lirik
Lagu ini dinyanyikan secara bersama dalam bentuk paduan suara dengan pembagian suara tertentu, terkhusus oleh kaum wanita dewasa dari keturunan keluarga Huwae dan Patty. Nyanyian ini diiringi dengan alat musik tifa, dengan tempo sedang. Ketiga bagian lagu ini diciptakan oleh oleh George Huwae pada tahun 1955, telah dinyanyikan kurang lebih tiga kali selama proses pelantikan raja pada tahun 1955, 1986 dan 2006. Lagu ini, menurut P. Huwae (wawancara pada tanggal 14 mei 2011), hanya diciptakan untuk keluarga Huwae dan keluarga Patty. Apabila keluarga dari marga yang lain diangkat menjadi raja, maka lagu yang dinyanyikan akan berbeda/lagu yang lainnya. Bahasa yang digunakan dalam lagu-lagu pelantikan raja adalah bahasa asli Maluku atau yang lazim disebut dengan istilah bahasa tanah.
b. Instrumen Musik
Instrumen yang digunakan untuk mengiringi lagu ini ialah dua buah tifa, yang berukuran sedang dan kecil. Kedua tifa ini masing-masing dimainkan dengan pola ritmis tertentu. Instrument ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan sebuah stik yang terbuat dari gaba-gaba (pelepah daun sagu). Tifa biasanya digunakan dalam upacara tradisional atau acara-acara penting lainya, misalnya penyambutan tamu kehormatan atau pejabat negara. Selain itu, tifa juga dimainkan untuk mengiringi berbagai tarian daerah Maluku seperti tari cakalele (tari perang), tari sau reka- reka, tari katreji (tari pergaulan).
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta.
Gambar 10. Tifa Maluku
Tifa terbuat dari sebatang kayu yang dilobangi, isinya dibuang, kemudian salah satu sisinya ditutupi dengan membran yang biasanya terbuat dari kulit rusa yang telah dikeringkan. Kulit rusa diyakini dapat menghasilkan suara yang lebih bagus dan indah saat didengar. Secara umum, bentuk tifa di tiap daerah Maluku hampir sama. Ada yang berbentuk gemuk pendek dan tinggi langsing. Semua bentuk yang dibuat disesuaikan dengan fungsi spesifik yang dimilikinya. Berdasarkan pola permainan dan fungsinya dalam sebuah penyajian musik, jenis-jenis tifa antara lain ialah sebagai berikut: tifa jikir, tifa tasa, tifa potong, tifa jekir potong dan tifa bass. Berikut ini adalah contoh pola permainan tifa-tifa tersebut.
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta.
Notasi 1. Motif-motif permainan tifa Maluku
2. Deskripsi dan Analisis Struktur dan Bentuk Kapata
a. Lagu dari Rumah Tua Huwae Ke Baeleo
Lagu pada bagian ini digunakan saat proses pelantikan raja sebagai lagu pengantar saat raja keluar dari rumah tua Huwae menuju rumah adat atau baeleo. Rumah tua Huwae yang menurut sejarah lisan adalah rumah dari saudara yang tua. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana raja yang dipilih atau diangkat sebagai pemimpin negeri Allang berasal dari keturunan keluarga Huwae. Masyarakat, khususnya keluarga Huwae, sangat mendukung atas diangkatnya saudara mereka. Berikut transkripsi lagunya.
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta.
Notasi 2. Lagu dari rumah tua Huwae ke baeleo
Arti lirik:
Hormat, hormat kami hormat, hormat raja kami hormat. Kami semua dengan bapa raja. Kami gendong kami dukung.
Lagu ini terdiri dari 8 birama dengan menggunakan tanda sukat 4/4. Dimulai pada birama gantung dengan menggunakan nada awal adalah nada 3 (mi) ketukan tiga, nilai not yang digunakan adalah not 1/16. Berakhir dengan nada 3 (mi) ketukan pertama menggunakan nilai not %.
Pada lagu ini terdapat dua kalimat lagu yaitu kalimat tanya dan dan kalimat jawab. Kalimat tanya dimulai dari 0/3 - 4/2, kalimat jawab dimulai dari 4/3 - 8/2. Dalam lagu ini terdapat anak kalimat yang terdiri dari beberap bagian. Anak kalimat pertama dimulai dari 0/3 - 2/1, kedua dimulai dari birama 2/3 - 4/2, ketiga dimulai dari 4/3 - 6/1, keempat dimulai dari 6/3 - 8/1. Figure dalam lagu ini terdapat beberapa figure yaitu; figure a dari 0/3 - 1/1, figure b dari 1/2 -2/1, figure c 2/3 - 3/1, figure d dari 3/2 - 4/1, figure e dari 4/3 - 5/1, figure f dari 5/2 - 6/1, figure g dari 6/3 - 7/1, figure h dari 7/2 - 8/1.
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta.
Notasi 3. Frase, anak frase, dan figure dalam lagu yang dinyanyikan dari rumah tua Huwae ke baeleo
Not yang digunakan dalam lagu ini sebanyak 7 buah nada antara lain 2 (re), 3 (mi), 4 (fa), 4 (fis), 5 (sol), 6 (la),7 (si). Not yang sering muncul pada lagu ini adalah not 5(sol) sebanyak 16 kali, yang jarang muncul not 4(fis) sebanyak satu kali. Not terendah adalah not 2 (re), not tertinggi 7 (si). Berikut ini tabel struktur lagu pertama:
b. Lagu dari Baeleo ke Rumah Patty
Pada saat raja keluar dari rumah adat atau baeleo menuju ke rumah tua Patty sebagai rumah keturunan marga Patty maka lagu ini dinyanyikan. Arti syair lagu ini ialah bahwa kita semua bersaudara, adik dan kakak, dilarang untuk berkelahi, jangan berselisih, dan yang bisa menyelesaikan pertengkaran itu hanya kita sendiri; semuanya harus satu dalam membangun negri Allang. Jelas terlihat ada suatu larangan dalam lagu ini. Berikut transkripsi lagunya.
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta.
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta.
Notasi 4. Lagu dari baeleo ke rumah tua Patty
Arti lirik:
Hormat, hormat kami hormat bapa raja yang baru. Kami minta semoga Tuhan memberkati. Kami ini adik kakak sayang. Jangan berkelahi, jangan rebut, kita semua yang kasih aman. Hei ibu bapak raja kami, pemuda- pemudi semua. Kita bangun negeri bangun jadi satu, kerja sama-sama. Bangun negeri kita, negeri Allang uru delapan.
Lagu ini terdiri dari 17 birama dengan menggunakan tanda sukat 4/4. Dimulai pada birama gantung dengan menggunakan not awal adalah not 5 (sol) ketukan tiga dengan menggunakan nilai not 1/16. Berakhir dengan nada 1 (do) ketukan pertama menggunakan nilai not penuh.
Pada lagu ini secara keseluruhan dapat dikelompokan menjadi dua bagian yaitu; bagian A dari (0/3 - 8/1) dan bagian B dari (9/1 - 17/1). Ini berarti lagu ini memiliki struktur bentuk dua bagian AB. Bagian A memiliki dua kalimat lagu yaitu kalimat tanya dan dan kalimat jawab. Kalimat tanya dimulai dari 0/3 - 4/1, kalimat jawab dimulai dari 4/3 - 8/1. Anak kalimat bagian A terdiri dari beberapa bagian, anak kalimat pertama dimulai dari 0/3 - 2/2, kedua dimulai dari birama 2/3 - 4/1, ketiga dimulai dari 4/3 - 6/2, keempat dimulai dari 6/3 - 8/1. Figure dalam lagu ini terdapat beberapa figure yaitu; figure a dari 0/3 - 1/1, figure b dari 1/2 -2/2, figure c 2/3 - 3/1, figure d dari 3/2 - 4/1, figure e dari 4/3 - 5/1, figure f dari 5/2 - 6/2, figure g dari 6/3 - 7/1, figure h dari 7/2 - 8/1. Bagian B memiliki dua kalimat lagu yaitu kalimat tanya dan dan kalimat jawab. Kalimat tanya dimulai dari 9/1 - 13/3, kalimat jawab dimulai dari 13/4 - 17/1. Anak kalimat bagian A terdiri dari beberapa bagian, anak kalimat pertama dimulai dari 9/1 - 12/1, kedua dimulai dari birama 12/2- 13/3, ketiga dimulai dari 13/4 - 15/1, keempat dimulai dari 15/3 - 17/1. Figure dalam bagian ini terdapat beberapa figure yaitu; figure a dari 9/1- 10/2, figure b dari 11/1 - 12/1, figure c 12/2 - 13/3, figure d dari 13/4 - 14/1, figure e dari 14/2 - 14/3, figure f dari 14/4 - 15/1, figure g dari 15/4 - 16/1, figure h dari 16/2 - 16/3, figure i 16/4 - 17/1.
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta.
Notasi 5. Bagian, frase,Lagu Anak frase dan figure dalam lagu yang dinyanyikan dari baeleo ke rumah tua Patty
Not yang digunakan dalam lagu ini sebanyak 8 buah nada antara lain 1(do), 2(re), 3(mi), 4 (fa), 4 (fis), 5(sol), 6(la),7(si). Not yang sering muncul pada lagu ini adalah not 5(sol) sebanyak 34 kali, yang jarang muncul not 7(si) sebanyak lima kali. Not terendah adalah not 1(do), not tertinggi 7(si). Berikut ini tabel struktur lagu pertama:
c. Lagu dari Rumah Patty ke Rumah Parintah
Lagu ini menceritakan bagaimana masyarakat Allang mendukung dan sangat menghargai raja yang baru ini untuk memimpin negeri di rumah perintah atau tempat raja tersebut melaksanakan tugasnya. Ada suatu penghargaan dan dukungan moril yang diberikan untuk raja yang baru dilantik ini. Berikut transkripsi lagu bagian ke tiga.
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta.
Notasi 6. Lagu dari rumah tua Patty ke rumah parintah
Arti lirik:
Hormat, hormat kami hormat bapa raja negeri Allang yang kami hormati. Bapak anak mara kolya. Kami minta dari Tuhan dan datuk-datuk kami gendong, kami dukung masuk rumah perintah. Hormat, bapa , hormat e.
Lagu ini terdiri dari 11 birama dengan menggunakan tanda sukat 4/4. Dimulai pada birama gantung dengan menggunakan nada awal adalah nada 5 (sol) ketukan tiga, nilai not yang digunakan adalah not 1/8. Berakhir dengan nada 1 (do) ketukan kedua menggunakan nilai not 1/2.
Pada lagu ini secara keseluruhan dapat dikelompokan menjadi dua bagian yaitu; bagian A dari (0/4 - 5/1) dan bagian B dari (5/4 - 11/2). Ini berarti lagu ini memiliki struktur bentuk dua bagian AB. Kedua bagian ini kemudian dapat dianggap setara degan kalimat, yaitu kalimat tanya dan dan kalimat jawab. Kalimat tanya dimulai dari 0/4 - 5/1, kalimat jawab dimulai dari 5/4 - 11/2. Anak kalimat bagian A terdiri dari beberapa bagian, anak kalimat pertama dimulai dari 0/4 - 2/1, kedua dimulai dari birama 2/2 - 4/1, ketiga dimulai dari 4/2 - 5/1. Figure dalam lagu ini terdapat beberapa figure yaitu; figure a dari 0/3 - 1/1, figure b dari 1/2 - 2/1, figure c 2/3 - 3/1, figure d dari 3/2 - 4/1, figure e dari 4/2 - 5/1. Bagian B memiliki beberapa bagian anak kalimat pertama dimulai dari 5/4 - 7/3, kedua dimulai dari birama 7/4 - 9/2, ketiga dimulai dari 9/3 - 11/2. Figure dalam bagian ini terdapat beberapa figure yaitu; figure a dari 5/46/3, figure b dari 6/4 - 7/3, figure c 7/4 - 8/2, figure d dari 8/3 - 9/2, figure e dari 9/3 - 10/2, figure f dari 10/3 - 11/2.
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta.
Notasi 7. Frase, anak frase, dan figure dalam lagu yang dinyanyikan dari rumah tua Patty ke rumah parintah
Not yang digunakan dalam lagu ini sebanyak 8 buah nada antara lain 1 (do), 2 (re), 3 (mi), 4 (fa), 4 (fis), 5 (sol), 6 (la), 7 (si). Not yang sering muncul pada lagu ini adalah not 5 (sol) sebanyak 19 kali, yang jarang muncul not 4 (fis) sebanyak satu kali. Not terendah adalah not 1 (do), not tertinggi i (do)1.
3. Tanda-tanda dan Makna Kapata
a. Tanda-tanda dalam Kapata
Tanda atau representamen menurut Peirce adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal. Sesuatu yang lain itu disebut interpretan dari tanda yang pertama yang mengacu pada Objek, dengan demikian sebuah tanda memiliki triadik langsung dengan interpretan dan objek (Budiman, 2003; 25).
Sebagai langkah awal untuk menjawab pertanyaan makna musik kapata pelantikan raja adalah melihat defenisi dari Nattiez (1990: 9) yang telah diterjemahkan tentang makna sebagai berikut: Sebuah objek apapun yang dijadikan makna atas pemahaman seseorang bahwa objek tersebut langsung menunjuk objek seseorang, dalam hubungan pengalaman hidupnya, yakni hubungan ke sebuah kumpulan objek lainnya, yang merupakan pengalaman seseorang di dunia.
Dengan demikian musik kapata pelantikan raja diciptakan oleh masyarakat Allang sebagai media penghubung kepada penguasa alam semesta sebagai ungkapan rasa syukur dan kepada sesama sebagai rasa solidaritas sebab telah hadir seorang pemimpin yang baru untuk memimpin negeri ini agar lebih baik dan maju.
Untuk mengungkapkan makna musik kapata pelantikan raja dengan semiotika, seperti yang dikatakan Peirce makna tanda adalah sebuah representamen dari suatu objek berdasarkan (ground) tanda lewat proses interpretasi yang menghasilkan interpretan. Objek dari tanda memiliki tiga sifat yaitu ikon, index dan symbol. Ground memiliki tiga dasar yaitu; qualisign, sinsign dan legisign. Interpretan memiliki tiga aspek yaitu; rheme, decisign dan argument.
Teori trikotomi dari Peirce:
1) Relasi tanda berdasarkan sifatnya dasarnya (ground) Qualisigns, Sinsign, Legisigns. Qualisigns dalah tanda- tanda yang merupakan tanda berdasarkan sesuatu sifat. Contoh ialah sifat merah atau hitam. Sinsign adalah tanda yang merupakan tanda atas dasar tampilannyadalam kenyataan. Contohnya antara lain, teriakan kesakitan, keheranan, kegembiraan. Legisigns adalah tanda-tanda yang merupakan tanda atas dasar suatu peraturan yang berlaku umum, sebuah konvensi, sebuah kode. Contoh rambu-rambu lalu lintas.
2) Relasi tanda dan objeknya terdiri dari; (1) ikon adalah hubungan antara tanda dan objek yang bersifat kemiripan sebagaimana dapat dikenali oleh para pemakainya, (2) indeks adalah hubungan tanda dan objek yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat yang memiliki keterkaitan fenomenal. dan (3) symbol adalah hubungan antara tanda dan ojek bersifat abitrer atau semena-mena, atau hubungan berdasarkan konvensi masyarakat.
3) Relasi tanda dengan interpretan antara lain; (1) Rheme meru-pakan tanda bila diinterpretasikan menghasilkan kemungkinan objek. (2) Dicisign merupakan tanda bila diinterpretasikan menghasilkan objek yang nyata. (3) Argument merupakan tanda bila diinterpretasikan menghasilkan objek yang benar dan berlaku umum.
Teori tripatisi semiotika Jean Molino yang ditulis dan dijabarkan oleh Jean-Jacquez Nattiez dalam bukunya yang berjudul Music and Discourse; Toward a Semiology of Music (1990: 11-12). Teori ini meng- gabungkan tiga demensi dari fenomena simbolis antara lain; (1) Dimensi poietic adalah bentuk simbolis proses karya musik dibuat (proses penciptaan). (2) Dimensi esthesic adalah bentuk simbolis dari hasil presepsi terhadap karya musik yang dibuat (proses pembentukan presepsia). (3) Dimensi trace adalah bentuk simbolis dari hasil pertunjukan karya (proses diatas panggung).
Music kapata pelantikan raja sebagai sebuah tanda bila dihu- bungkan dalam trikotomi Peirce antara lain; tiga trikotomi yang pertama adalah hubungan tanda dengan tanda itu sendiri (ground), yang memiliki aspek qualigsign, sinsign dan legisign. Bagi masyarakat yang baru pertama kali mendengarkan kapata pelantikan raja di negeri Allang diasumsikan sebagai qualisign ini disebakan karena tidak memahami apa maksud dari lagu itu. Sedangkan bagi bagi masyarakat Allang sendiri kapata ini memiliki arti dan makna bagi mereka inilah yang disebut sebagai aspek sinsign. Terkhusus bagi marga Huwae dan Patty kapata ini sebagai aspek legisign dikarenakan lagu ini hanya mereka saja yang bisa menya- nyikannya dengan kata lain merupakan sebuah aturan.
Tiga trikotomi yang kedua adalah hubungan tanda dengan objek, yang memiliki aspek ikon, index dan symbol. Music kapata pelantikan raja bagi masyarakat Allang sendiri diasumsikan sebagai sebuah symbol atau tanda konvensional, dan bagi masyarakat di luar Allang menjadi tanda indeks apabila mendengarkan lagu ini akan menjadi sebuah petunjuk inilah ciri dari lagu-lagu Ambon yang berirama tifa.
Trikotomi yang ketiga adalah hubungan tanda dengan interpretan, yang memiliki aspek rheme, dicisign dan argument. Untuk menjawab trikotomi yang ketiga ini maka terlebih dahulu memahami empat macam cara mendengarkan musik yang diungkapkan oleh Miller dalam buku pengantar apresiasi musik, yakni; (1) Mendengarkan secara pasif, (2) mendengarkan secara menikmati, (3) Mendengarkan secara emosional, (4) mendengarkan secara perseptif. Dengan demikian musik kapata pelan-tikan raja bagi masyarakat diluar Allang akan memahami itu sebagai sebuah pertunjukan seni dalam bentuk tradisional inilah disebut aspek dicisign, ini disebabkan karena masyarakat di luar Allang hanya mendengar lantunan lagu ini sebatas mendengarkan secara pasif dan sebatas menikmati pementasan tersebut. Bagi masyarakat Allang sendiri kapata ini merupakan aspek argument, karena masyarakat mendengarkan lagu selain dari menikmati tetapi juga mendengar dengan emosional dan perseptif.
b. Makna Kapata
Untuk menjelaskan makna dari tanda-tanda pada kapata pelantikan raja akan dijelaskan berdasarkan analisis srtuktur musik pada bab terdahulu, yakni sebagai berikut.
1) . Nada
Simbol dari bunyi menghaslikan nada/tone, nada/tone adalah bunyi yang lahir dari not, berdasarkan pengertian ini sebuah nada akan menjadi qualisign ketika dibunyikan atau didengar. Sebuah nada dibu- nyikan untuk mencari tonika akan menjadi sebuah tanda legisign dan bila dihububgkan dengan intrepretan akan menjadi aspek argument, dan bila dihubungkan dengan objeknya akan menjadi symbol.
Tabel. Jumlah nada pada kapata yang dinyanyikan dalam upacara pelantikan raja Allang
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Pada lagu bagian pertama terdapat 7 buah nada seperti terlihat pada gambar notasi 2. Pada proses semiosis tingkat pertama, penggunaan tujuh buah nada dalam lagu kedua ini merupakan prinsip kemiripan (similarity) tanda ikon diagramtik sebagai representamen yang merujuk pada angka- angka. Selanjutnya, pada proses semiosis representamen yang berikut, angka-angka merupakan prinsip kausal, yaitu tanda indeksikal yang merujuk pada objek perkampungan masyarakat Allang di daerah pegunungan yang ditemukan oleh para leluhur imigran dari Seram ber- jumlah tujuh buah hena atau negri yakni; (1) Hinamutua; (2) Heiua Suing; (3) Hinatueng; (4) Hiaowolit; (5) Huiaanou; (6) Neinamale; dan (7) Henaitu.
Ketujuh negeri ini sampai sekarang dianggap sebagai negeri lama masyarakat Allang. Untuk lebih jelasnya tentang proses semiosis ini, perhatikan bagan berikut (Keterangan: R = representamen, O = objek).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gambar 11. Proses semiosis penggunaan tujuh buah nada merujuk pada tujuh buah kampung
Lagu bagian kedua terdapat delapan buah not seperti terlihat pada gambar notasi 4. Pada proses semiosis tingkat pertama, penggunaan delapan buah not dalam lagu kedua ini merupakan prinsip kemiripan (similarity) tanda ikon diagramtik sebagai representamen yang merujuk pada angka-angka. Selanjutnya, pada proses semiosis representamen yang berikut, angka-angka merupakan prinsip kausal, yaitu tanda indeksikal yang merujuk pada objek sistem kehidupan sosial orang Allang yang tergabung dalam delapan soa. Untuk lebih jeasnya tentang proses semiosis ini, perhatikan bagan berikut.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gambar 12. Proses semiosis penggunaan delapan buah nada merujuk pada delapan soa
Lagu ketiga terdapat sembilan buah not seperti terlihat pada gambar notasi 6. Pada proses semiosis tingkat pertama, penggunaan sembilan buah nada dalam lagu ini merupakan prinsip kemiripan (simila-rity) tanda ikon diagramtik sebagai representamen yang merujuk pada angka-angka. Selanjutnya, pada proses semiosis representamen yang berikut, angka- angka merupakan prinsip kausal, yaitu tanda indeksikal yang merujuk pada objek salah satu sistem kehidupan sosial orang Allang . Masyarakat Allang tergolong dalam kelompok Patasiwa. Patasiwa adalah satu dari dua kelompok sosial masyarakat yang terdapat di pulau Seram. Kelompok ini dapat diidentifikasi antara lain melalui benda-benda atau simbol-simbol berjumlah sembilan yang digunakan dalam ritual (Ajawaila, 2000: 17).
Untuk lebih jelasnya tentang proses semiosis ini, perhatikan bagan berikut.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gambar 13. Proses semiosis penggunaan sembilan buah nada merujuk pada kelompok PataSiwa
Penggunaan tujuh, delapan dan sembilan buah nada yang diguna- kan dalam ketiga lagu ini apabila dipahami adalah sebuah objek yang dikategorikan sebagai aspek legisign dan symbol, dan bagi masyarakat Allang lagu ini diasumsikan sebagai sebuah argument.
2) . Melodi
Pada bagian ini akan di lihat arah gerak/ melodic countour dari ketiga bentuk lagu yang disajikan dalam acara pelantikan raja. Penggu-naan arah gerak dalam bentuk grafik ini akan memperjelas makna tanda-tanda dalam kapata berdasarkan simbol-simbol musikal baik melodi dan interfal yang digunakan dalam kapata yang memiliki makna metafora alam Maluku, untuk lebih jelasnya akan di jelaskan dengan grafik dibawah ini:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gambar 14. Kontur melodi lagu yang dinyanyikan dari rumah tua Huwae ke baeleo
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gambar 15. Kontur melodi lagu yang dinyanyikan dari baeleo ke rumah tua Patty
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gambar 16. Kontur melodi lagu yang dinyanyikan dari rumah tua Patty ke rumah parintah
Keterangan: Interval antara nada satu dengan nada berikutnya bermacam macam, antara lain sekonde kecil (misalnya dari 3 (mi) ke 4 (fa), dan sejenisnya), terts besar (misalnya dari 5 (sol) ke 7 (si)).
Ketiga bentuk lagu ini arah gerak alur melodi kadangkala bergerak naik, bertahan, kemudian melangkah turun dan seterusnya. Lagu inipun memiliki beberapa interval antara lain interval kecil, interval besar dan interval murni. Baik arah gerak melodi maupun interval terlihat laksana gunung dan ombak yang berada di pesisir pantai. Pada proses semiosis tingkat pertama, arah gerak/ melodic contour dalam lagu ini merupakan prinsip similarity tanda ikon diagramtik sebagai representamen yang merujuk pada objek gunung. Selanjutnya, pada proses semiosis yang kedua, representamennya, yaitu interval merujuk pada objek ombak. Objek pertama, yaitu gunung, ada yang tinggi, rendah, besar, kecil, dan bergelombang; sedangkan objek kedua, yakni ombak, ada pula yang tinggi, rendah, besar, kecil, dan bergelombang. Dengan demikian, ada kesamaan pada kedua objek tersebut. Jelas, bagian ini merupakan metafora dari alam Maluku yang dikelilingi oleh lautan dan pegunungan. Melodi dan interval merupakan sinsign, bahkan juga sebagai rheme, inilah yang disebut dengan sinsign ikonis. Arah gerak/ melodic contour bisa dilihat pada gambar di atas. Untuk lebih jeasnya tentang proses semiosis ini, perhatikan bagan berikut.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gambar 17. Proses semiosis ikon metafora
3) . Ritme
Ritme yang digunakan dalam ketiga bentuk lagu ini adalah Ritme yang digunakan adalah isorhytm 2 satu pola ritme pendek yang diulang- ulang dengan mengunakan not penuh, not %, not % dan not 1/8, not 1/16 dengan tempo lambat. Pada proses semiosis, penggunaan ritme yang berulang-ulang dan lambat merupakan prinsip kausal tanda indeksikal, sebagai representamen yang merujuk pada objek cara menyampaikan pesan dalam sebuah berita. Agar pesan yang akan disampaikan melalui nyanyian ini dapat seluruhnya didengar dan dimengerti dengan baik, maka pesan tersebut terpaksa diulang-ulang dan disampaikan dengan lambat. Apabila nyanyian ini menggunakan not 1/32, not 1/64 dan dengan tempo yang cepat serta pola ritme yang berubah-ubah, mungkin saja pesan yang disampaikan kepada orang tersebut tidaklah jelas, sehingga pesan tersebut tidak mudah untuk dimengerti. Ini disebabkan karena pada not-not 1/32, 1/64 cenderung cepat dan pola ritmenya selalu berubah-ubah, sehingga membuat pesan ini akan lambat dimengerti dan dipahami. Dalam lagu ini, ritme yang lambat dan ketukan yang diulang-ulang merupakan sinsign. Keserupaan antara ritme (dengan tempo lambat dan pola berulang-ulang) dengan cara penyampaian pesan ini dapat dilihat sebagai rheme. Inilah yang disebut sinsign indeksikal rhematis. 4) . Figure
Menurut Leon Stein (1979: 3) figure adalah bagian terkecil dalam konstruksi musik, setidaknya terdiri dari karaktersitik ritmis dan interval yang sama. Ia dapat juga terdiri mulai dari dua hingga dua belas nada. Itu berarti terdapat penggabungan beberapa nada atau beberapa qualisign yang berbeda merupakan sinsign karena memiliki interval dan ritme yang dapat diinterpretasikan. Apabila dihubungkan dengan interpretan akan mengha- silkan dicisign yang merujuk pada sebuah figure.
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta. Notasi 8. Contoh figure
5) . Semi Frase
Pada prinsipnya penggabungan beberapa buah figure disebut anak frase, semi frase dapat dikatakan sebagai sinsign. Jika dihubungkan dengan interpretan akan menghasilkan dicisign yaitu sebuah anak frase, dan bila dihubungkan dengan objek akan menjadi sebuah symbol yang bersifat konvensional.
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta.
Contoh 9. Contoh semi frase
6) . Frase
Suatu frase biasanya terdiri dari empat birama, dan ditentukan oleh kadens. Penggabungan beberapa buah anak frase disebut frase, ini merupakan legisign, karena menjadi sebuah aturan dalam musik. Apabila dihubungkan dengan interpretan akan menghasilkan rheme dan dapat juga menjadi sinsign apabila dimengerti oleh seseorang.
7) . Periode
Periode biasanya terdiri dari dua frase, yang pertama anteseden dan kedua disebut konsouken. Periode merupakan sebuah legisign karena memiliki beberapa frase, baik itu frase tanya maupun frase jawab. Bila dihubungkan dengan interpretan akan menghasilkan sebuah argument, dan akan dilihat sebagai tanda sinsign bila sesorang memahami itu secara terbatas.
Catatan editor: Gambar telah dihapus karena alasan hak cipta.
Notasi 11. Contoh sebuah periode
Ketiga lagu dalam kapata pelantikan raja sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan, solidaritas terhadap sesama, motifasi untuk membangun, rasa kecintaan terhadap negeri, sebagai bentuk kerja sama untuk menjaga kesatuan dan persatuan, rasa hidup bersaudara layaknya adik dan kakak.
Struktur lagu kapata pelantikan raja apabila dipahami adalah sebuah objek yang dikategorikan sebagai aspek legisign dan symbol, dan bagi masyarakat Allang lagu ini diasumsikan sebagai sebuah argument seperti yang dijelaskan di atas. Sebagai penulis, dalam hal ini menjadi tanda kedua atas tanda yang pertama. Makna lagu yang diungkapkan oleh P. Huwae adalah tanda pertama sebagai argument, penulis adalah tanda kedua memaknai lagu kapata pelantikan raja ini sebagai sebuah argument.
Makna musik kapata pelantikan raja akan dilihat lewat teori semiotika tripatisi yaitu; poietic, trace dan esthesic. Masyarakat Allang adalah produser atau komponis dalam kapata pelantikan raja sebagai proses dimensi poietic. Sebagai dimensi trace kapata pelantikan raja merupakan symbol yang diwujudkan dalam pentuk pertujunkan seperti dijelaskan pada bab terdahulu. Dalam dimensi esthesic adalah mereka semua yang menjadi pendengar lewat prespsi dan interpretasi mereka. Itu berarti baik yang diluar masyarakat Allang dan masyarakat Allang sendiri dikategorikan dalam dimensi ini lewat pemahaman mereka tentang makna kapata pelantikan raja.
B) Transmisi Kapata
Transmisi merupakan salah satu aspek penting dalam kontinuitas suatu kebudayaan secara umum, dan seni secara khusus. Dalam budaya- budaya musik di Indonesia, dan budaya-budaya Timur umumnya, trans-misi berlangsung secara oral. Ilmu, pengetahuan, serta kemampuan teknik dari musisi-musisi ditransferkan kepada generasi berikutnya secara lisan, tanpa bantuan notasi-notasi tertulis seperti halnya dalam pembelajaran musik di Barat. Metode transmisi seperti ini juga ditemui dalam budaya musik Maluku, termasuk dalam pentransmisian kapata. Seseorang yang ingin belajar tidak belajar secara khusus kepada musisi-musisi yang ada, melainkan hanya melihat dan mendengarkan apa yang dimainkan oleh para musisi tersebut. Gambar dibawah ini akan menjelaskan bagaimana proses transmisi kapata berlangsung dalam kehidupan masyarakat Allang.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gambar 18. Proses Transmisi kapata
Akan tetapi, keadaan seperti ini mulai berubah seiring dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat setempat, serta pengaruh- pengaruh yang datang dari luar, khususnya pengaruh musik dari luar Maluku (khususnya musik barat). Notasi mulai digunakan dalam proses pentransmisisan musik-musik Maluku, termasuk kapata. Proses pentrans- misian kapata yang dinyanyikan dalam pelantikan raja Allang, yang dulunya bersifat oral, kini mulai menggunakan sistem tulisan. P. Huwae, seorang musisi lokal yang cukup dipandang oleh masyarakat negri Allang, mulai menggunakan sistem notasi angka dalam proses pembe-lajaran kapata kepada kaum wanita dalam masyarakat itu, yang nantinya akan menyanyikan kapata-kapata tersebut dalam pelantikan raja mereka. Di satu sisi, penggunaan notasi pembelajaran kapata menyebabkan komposisi nyanyian menjadi lebih ‘rapi.’ Para penyanyi memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana mereka menyanyi, nada-nada apa saja yang harus dilantunkan, sehingga harmonisasi antara jenis suara satu dengan suara yang lainnya menjadi lebih ‘sinkron.’ Di sisi lain, ‘kebebasan’ penyanyi menjadi sedikit terbatas karena penggunaan notasi. Ini menujukkan adanya keterkaitan antara bunyi musik, perilaku, serta konsep-konsep yang ada di balik musik tersebut (Merriam, 1964: 32).
Pembelajaran kapata untuk pelantikan raja Allang biasanya dilakukan beberapa hari sebelum acara tersebut dilangsungkan. Waktu untuk berlatih tergantung dari waktu yang disediakan oleh penye- lenggara, namun biasanya dilakukan setelah diketahui siapa yang terpilih menjadi raja. Para penyanyi, yakni para wanita dewasa dalam masyarakat tersebut, datang berkumpul di tempat yang telah ditentukan, dan mulai bernyanyi menggunakan notasi, dengan dibimbing oleh ‘pelatih,’ yakni P. Huwae.
Kay Kaufman Shelemay mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga jenis pekerjaan dalam transmisi tradisi, yakni (1) memelihara tradisi, (2) mengenang tradisi, dan (3) memediasi tradisi (1997: 197-200). Ketiga pekerjaan ini tidak dapat dipisahkan secara kaku, melainkan saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Ketika kapata disajikan dalam pelantikan raja Allang, maka tradisi masyarakatnya secara langsung terpelihara. Ada semacam upaya untuk meneruskan keber-langsungan warisan para leluhur—yakni kapata —ketika tindakan seperti ini dilakukan. Pada dasarnya tidak hanya musik atau kapata saja yang terpelihara, melainkan juga berbagai apsek pendukungnya, seperti bahasa lokal, yakni bahasa tanah, pesan-pesan leluhur, dan sebagainya.
Pemeliharaan ini juga berarti mengenang apa yang telah diwaris-kan para leluhur negri Allang kepada generasi saat ini. Di satu sisi, penyajian kapata dalam pelantikan raja negri Allang berarti mengenang adanya kapata itu sendiri; di sisi lain, penyajian kapata juga berarti mengenang masa lalu dan tradisi yang dimiliki oleh negri dan masyarakat Allang. Ketika kapata terus dipelihara dan dikenang, pada gilirannya ia akan dikenal oleh masyarakat, baik masyarakat Allang secara khusus, dan masyarakat Maluku dalam konteks yang lebih luas. Di sinilah mediasi tradisi terjadi, yakni inti dari proses transmisi itu sendiri. Penyajian kapata dalam pelantikan raja Allang, dalam tataran tertentu, dapat dipandang sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensi nyanyian tersebut, sehingga ia dikenal, dipelajari, dinyanyikan, hingga pada akhirnya keberlangsung- annya tetap terjaga.
Pemeliharaan ini juga berarti mengenang apa yang telah diwaris-kan para leluhur negri Allang kepada generasi saat ini. Di satu sisi, penyajian kapata dalam pelantikan raja negri Allang berarti mengenang adanya kapata itu sendiri; di sisi lain, penyajian kapata juga berarti mengenang masa lalu dan tradisi yang dimiliki oleh negri dan masyarakat Allang. Ketika kapata terus dipelihara dan dikenang, pada gilirannya ia akan dikenal oleh masyarakat, baik masyarakat Allang secara khusus, dan masyarakat Maluku dalam konteks yang lebih luas. Di sinilah mediasi tradisi terjadi, yakni inti dari proses transmisi itu sendiri. Penyajian kapata dalam pelantikan raja Allang, dalam tataran tertentu, dapat dipandang sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensi nyanyian tersebut, sehingga ia dikenal, dipelajari, dinyanyikan, hingga pada akhirnya keberlangsung- annya tetap terjaga.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
Hasil analisis pada kapata pelantikan raja lewat kajian semiotika teori trikotomi Peirce telah menunjukkan bahwa lagu-lagu yang disajikan dalam acara pelantikan raja di Allang memiliki arti dan makna dari tanda-tanda yang terdapat dalam nyanyian tersebut dalam hal ini struktur musik dan syair lagu. Tanda-tanda ini dapat diterima di masyarakat sebagai suatu kode kultural dalam kapata yang menjadi bahan kajian.
Proses transmisi kapata berlangsung secara oral. Namun, seiring dengan masuknya pengaruh luar, yang juga berdampak pada mening- katnya pengetahuan musisi-musisi lokal, kini juga telah digunakan notasi dalam pembelajaran kapata. Ini cukup berdampak pada gaya nyanyian kapata, yakni menjadi lebih ‘rapi,’. Proses transmisi kapata setidaknya terjadi dalam tiga bentuk, yakni dengan memelihara, mengenang, dan memediasinya. Ketika bentuk atau jenis ini tidak dapat dipisahkan secara kaku, melainkan tumpang tindih dan saling koheren antara satu dengan yang lainnya.
B. Saran
Upaya pelestarian musik kapata perlu ditingkatkan lagi. Ternyata pelestarian musik kapata hanya sebatas mentransfer kapata tersebut kepada generasi saat ini lewat cara oral, dilakukan pada saat-saat tertentu saja, misalnya waktu peryaan-perayaan ritual yang berlangsung. Oleh karena itu, nyanyian rakyat/ folk songs kapata yang berada di daerah Maluku perlu dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi muda di daerah ini. Ini penting, sebab nyayian rakyat memiliki akar kuat dalam kebudayaan, perkembangan mayarakat, perkembangan sejarah dan peradaban yang mengandung nilai-nilai luhur. Selain itu, pelestarian seperti ini memiliki konstribusi yang besar bagi perkembangan musik di daerah ini, khu- susnya di daerah kota Ambon dan sekitarnya sebagai the brith place atau tempat kelahiran dari musik itu sendiri.
SUMBER ACUAN
A. Literatur
Agawu, Kofi. 2009. Music as Discourse: Semiotic Adventures in Romantic Music. Oxford & New York: Oxford University Press.
Ajawaila, Jacob W. 2000. “Orang Ambon dan Perubahan Kebudayaan.” Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology, Tahun XXIV, No. 61.
Boland, M C. 1983. Uru, Son of The Sunrise atau Uru, Bahasa dan Kapata, terjemahan S.J.M. Sihauta.
Budiman, Kris. 2004. Semitotka Visual. Yogyakarta: Buku Baik.
Bramantyo Triyono. 2004. Disseminasi Musik Barat Di Timur. Yogya-karta: Yayasan Untuk Indonesia.
Danandjaja, James. 1986. Folklore Indonesia. Jakarta: Grafiti Press.
Feld, Steven. 1974. “Linguistic Models in Ethnomusicology.” Ethnomusicology Vol. XVIII, No. 2.
Karl-Edmund Prier SJ. 1991. Sejarah Musik Jilid I, Pusat Musik Liturgi, Yogyakarta.
Lomax, Alan. 1968. Folk Song Style and Culture. Brunswick, New Jersey: Transction Books.
Mack, Dieter. 1995. Apresiasi Musik Pop. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
Merriam, Alan P. 1964. The Anthropology of Music. Evanston, Illinois: Northwestern University Press.
Matulessy, Z M . 1978. Hikayat Nunusaku. Ambon: Departemen Pendi- dikan dan kebudayaan Propinsi Maluku.
Nattiez, Jean-Jacques. 1990. Music and discourse: toward a semilogy of music. New Jersey: Princeton University Press.
Noth Winfried. 1990. Handbook of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press.
Pattikayhatu J.A. at all. 1993. Sejarah Daerah Maluku Ambon: Departe-men Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku.
Pattikayhatu J.A. 2003. “Sejarah Negeri Allang dan Kehidupan Budaya Masyarakatnya“. Makalah disajikan dalam seminar sejarah negeri Allang yang diselanggarkan oleh, panitia seminar sejarah negeri Allang.
Seeger, Charles. 1982. “Foreword,” dalam Mantle Hood, The Ethnomusicologist. Kent, Ohio: Kent State University Press.
Shelemay, Kay kaufman. 1997. “Ethnomusicologist, Ethnographic Method and the ransmission of tradition,” dalam Gregory f. Barz dan Timothy J. Cooley, ed. Shadows in the Field: New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology. Oxford: Oxford University Press.
Siyauta, Saul. 1986 dalam artikel Mengenal SiwaLima Mengenal Jatidiri.
Stein, Leon. 1979. Structure and Style: The Study and Analysis of Musical forms. New Jersey: Summy-Birchard Music.
Tamaela, Christian I. 1995. Gereja Pulau-pulau Toma Arus Sibak Ombak Tegar: Musik Maluku Sebagai Saranan Komunikasi Injil Dalam Jemaat GPM. Ambon: Fakultas Teologi UKIM.
Tim Koordinasi Siaran Direktorat Jenderal Kebudayaan. 1991/1992. Aneka Ragam Khasanah Budaya Nusantara II. Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan.
Tim Taman Budaya Provinsi Maluku. 2004. Kapata: Nyanyian Tradisi di Maluku. Ambon: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku.
Zoest, Aart van. 1993. Semiotika: Tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa yang Kita Lakukan Dengannya. Terjemahan Ani Soekawati. Jakarta: Yayasan Sumber Agung.
B. Narasumber
Petrus Huwae, 65 tahun, sebagai tokoh adat dan pelatih musik di Negeri Allang.
David Patty, 45 tahun, sebagai sekretaris Negeri Allang
Pdt. Stefanus Sipahelut (alm.), 51 Tahun, mantan ketua Saniri Negeri Allang.
Rudolof Patty, 57 tahun, Raja Negeri Allang
Hibert Patty, 50 Tahun, staf pemerintah Negeri Allang
Buang Ralahalu, 72 tahun, tokoh adat Negeri Allang
Yacob Huwae, 70 tahun, tokoh adat Negeri Allang
C. Diskografi
CD acara pelantikan raja di Negeri Allang tahun 2006, direkam oleh panitia pelaksana pelantikan raja.
CD lagu yang disajikan dalam acara pelantikan raja yang dinyanyikan oleh narasumber pada tgl 15 Mei 2011 di Allang.
[...]
1 Hasil analisis bentuk lagu digunakan untuk memperjelas hasil analisis teori trikotomi Peirce untuk mengungkapkan makna tanda-tanda apa saja dalam kapata.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu Kapata?
Kapata adalah genre folksong (nyanyian rakyat) di Maluku Tengah. Biasanya dinyanyikan atau dilafalkan seperti sajak dan sering ditampilkan dalam upacara ritual adat.
Apa saja upacara yang biasanya menampilkan Kapata?
Kapata seringkali ditampilkan saat pelantikan Raja (Raja), renovasi rumah adat (baeleo), dan peresmian bangunan baru.
Apa pendekatan penelitian yang digunakan dalam analisis Kapata?
Pendekatan yang digunakan adalah etnomusikologi dan analisis semiotika berdasarkan teori trikotomi Peirce.
Apa saja teori yang digunakan untuk menganalisis Kapata?
Teori utama yang digunakan adalah teori trikotomi Peirce dan teori Merriam tentang tiga level aktivitas musikal (konsep, perilaku, dan bunyi musik).
Apa itu teori trikotomi Peirce?
Teori yang membahas relasi tanda berdasarkan sifat dasarnya (qualisigns, sinsign, legisigns), relasi tanda dan objeknya (ikon, indeks, symbol), serta relasi tanda dengan interpretan (rheme, decisign, argument).
Apa itu teori Merriam?
Teori yang menyatakan bahwa musik sebagai bunyi dipengaruhi oleh konsep yang ada pada masyarakat pemilik musik, dimana konsep tersebut kemudian berpengaruh pada perilaku masyarakat dalam bermusik.
Apa itu Negeri Allang?
Negeri (desa) yang terletak di jazirah Leihitu, Pulau Ambon, pintu masuk Teluk Ambon, yang memiliki sejarah dan budaya yang khas.
Apa pengaruh budaya luar terhadap musik di Maluku?
Terdapat pengaruh dari musik Timur Tengah (seperti sawat dan hadrat) serta musik Eropa (seperti penggunaan suling bambu dan tangga nada diatonik).
Apa saja jenis-jenis Kapata?
Jenis-jenis Kapata meliputi Kapata Hasurite (untuk upacara resmi), Kapata Mako-mako (untuk doa dan pengucapan syukur), dan Kapata Cakalele (untuk persiapan perang dan menyambut kemenangan).
Bagaimana proses transmisi Kapata berlangsung?
Awalnya, transmisi berlangsung secara oral. Namun, saat ini notasi mulai digunakan dalam proses pembelajaran, yang sedikit mengubah gaya nyanyian Kapata.
Apa makna tanda-tanda dalam Kapata pelantikan raja Allang?
Tanda-tanda tersebut merepresentasikan kode-kode kultural, sejarah masyarakat Allang, sistem kehidupan sosial (soa dan Patasiwa), serta metafora alam Maluku (gunung dan ombak).
Apa saja instrumen musik yang digunakan dalam Kapata pelantikan raja Allang?
Instrumen utamanya adalah tifa, dimainkan dengan pola ritmis tertentu.
Apa struktur lagu yang digunakan dalam Kapata pelantikan raja Allang?
Struktur lagunya bervariasi, tetapi seringkali terdiri dari dua bagian (A dan B) dengan kalimat tanya dan jawab.
Apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melestarikan Kapata?
Langkah-langkah tersebut meliputi memelihara tradisi, mengenang tradisi, dan memediasi tradisi (mengenalkan Kapata kepada masyarakat luas).
Mengapa Kapata penting bagi masyarakat Maluku?
Kapata merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Maluku, mengandung nilai-nilai filosofis, sejarah, dan spiritual yang diwariskan oleh para leluhur.
Siapa saja narasumber yang memberikan informasi tentang Kapata dalam penelitian ini?
Petrus Huwae, David Patty, Pdt. Stefanus Sipahelut (alm.), Rudolof Patty, Hibert Patty, Buang Ralahalu, dan Yacob Huwae.
- Quote paper
- Nelsano A Latupeirissa (Author), 2011, Kapata Dalam Kajian Semiotika Menurut Teori Trikotomi Peirce, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1183340